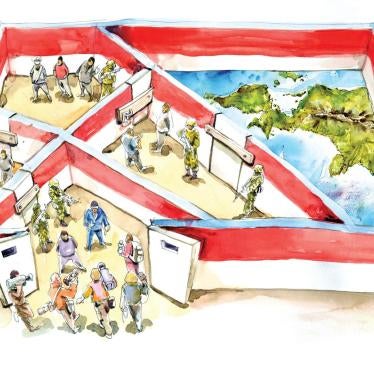Oleh: Andreas Harsono
“Media yang bebas, tentu saja, bisa baik dan bisa buruk. Namun tanpa kebebasan pers, media akan selalu buruk.”
Albert Camus
Pada Juni 1994, pemerintah Indonesia menutup tiga mingguan berita—Detik, Editor dan Tempo—yang memicu protes luas terhadap peraturan soal izin terbit dari pemerintah terhadap semua surat kabar. Ratusan wartawan protes pembredelan tersebut. Mereka menuntut agar Persatuan Wartawan Indonesia minta Presiden Soeharto mencabut keputusan pembredelan. Persatuan Wartawan Indonesia, sebuah organisasi yang tak independen dari pemerintah, mengeluarkan siaran pers, isinya mengatakan bahwa mereka “memahami” keputusan Soeharto.
Lebih dari seratus jurnalis yang geram, termasuk beberapa wartawan senior dan kolumnis, memutuskan untuk melawan pemerintah yang lalim. Saya termasuk salah satunya. Kami berkumpul di sebuah vila di Desa Sirnagalih, Bogor, sekitar dua jam naik mobil dari Jakarta, pada Agustus 1994. Kami bikin deklarasi bahwa kami akan memperjuangkan kebebasan pers dan kesejahteraan awak media. Ia dilakukan dengan organisasi baru: Aliansi Jurnalis Independen.
Kami tidak naif. Kami tahu itu tindakan ilegal karena saat itu pemerintah Indonesia hanya mengizinkan wadah tunggal untuk wartawan. Kami sadar bahwa Departemen Penerangan, polisi, militer, dan Persatuan Wartawan Indonesia akan bertindak menindas kami. Beberapa bulan kemudian, belasan jurnalis yang ikut deklarasi, termasuk saya, kehilangan pekerjaan dan dilarang bekerja untuk media manapun di Indonesia. Polisi bahkan menangkap beberapa jurnalis dan menggiring mereka ke pengadilan. Dan hakim-hakim yang berpikiran sempit, yang hanya berpikir soal kesejahteraan mereka, mengeluarkan vonis hukuman penjara. Sebagian jurnalis memutuskan keluar dari Indonesia.
Namun ia juga babak baru, setidaknya bagi saya, yang membuat kami belajar tentang situasi kebebasan pers di Asia. Saya belajar tentang perlunya ombudsman di ruang redaksi terutama media besar. Jurnalis harus transparan soal motivasi dan metode mereka dalam meliput dan menulis berita. Jika mereka membuat kesalahan, mereka harus lakukan ralat dan minta maaf. Seperti Albert Camus dari Prancis menulis, “Media yang bebas, tentu saja, bisa baik dan bisa buruk. Namun tanpa kebebasan pers, media akan selalu buruk.”
Pada Januari 1995, Aliansi Jurnalis Independen yang baru berumur lima bulan mendapat undangan mengikuti sebuah konferensi di Hong Kong soal pembatasan pers di Indonesia. Di Hong Kong, saya bertemu dengan banyak jurnalis Asia lainnya, termasuk Jimmy Lai, pemilik Apple Daily di Hong Kong.
Pana Janviroj, pemimpin redaksi harian The Nation di Bangkok, juga bicara di konferensi. Kami kebetulan duduk dalam limousin sama yang disediakan Freedom Forum, organisasi asal Amerika Serikat, yang juga mensponsori pertemuan, dari Hotel Grand Hyatt di Wanchai menuju makan malam mewah dengan Foreign Correspondent Club.
Pana bertanya, “Apakah mau gabung dengan kami?”
Gaji bulanannya hampir lima kali lipat gaji saya sebelumnya, ditambah saya masih bisa menulis untuk surat kabar lain. Tentu saja, saya bilang oke. Tak ada surat lamaran. Tak ada kontrak. Hanya jabat tangan.
Dia minta saya untuk segera terbang ke Bangkok. Dia memperkenalkan saya kepada beberapa editornya: Kavi Chongkittavorn, Sonny Inbaraj, Steven Gan, Yindee Lertcharoenchok serta penyiar televisi mereka Thepchai Yong.
Saya mulai mengirimkan laporan pada Maret 1995, bekerja dari Jakarta, kemudian juga dari Phnom Penh, Yangon, dan Kuala Lumpur. Saya tak diberi kuota, hanya diminta menulis minimal sekali seminggu, tetapi kalau ada breaking news, tentu saja, saya menulis banyak. Saya meliput berbagai macam cerita, termasuk Hun Sen singkirkan Norodom Ranariddh di Kamboja, politikus Myanmar Aung San Suu Kyi yang jadi tahanan rumah, krisis ekonomi Asia, serta ketegangan di Timor Leste. Aung Zaw, seorang jurnalis Burma, juga bergabung dengan kami dari Chiang Mai, kebanyakan menulis tentang junta militer di Myanmar.
Di Jakarta, saya mengenal koresponden CNN Maria Ressa, yang meliput kerusuhan tahun 1996 saat pemerintah Presiden Soeharto melakukan manipulasi terhadap partai politik pimpinan Megawati Soekarnopoetri.
Saya mulai bertemu dengan banyak tokoh jurnalisme yang penuh semangat di Asia Tenggara. Sheila Coronel, yang membantu mendirikan Philippines Centre for Investigative Journalism, setuju untuk melatih jurnalis Indonesia di Medan, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar pada 1997-1998. Saya juga menikmati persahabatan dengan banyak jurnalis Far Eastern Economic Review di Hong Kong.
Saya bantu mendirikan sejumlah kelompok advokasi hak media, antara lain Institut Studi Arus Informasi bersama Goenawan Mohamad, Isaac Santoso, Yosep Adi Prasetyo dan lain-lain. Di Bangkok, Coronel, Chongkittavorn, dan jurnalis lainnya mendirikan South East Asia Press Alliance atau Aliansi Pers Asia Tenggara (SEAPA) pada tahun 1997, untuk memperjuangkan kebebasan pers di kawasan ini.
Krisis ekonomi Asia, yang muncul pada Juli 1997, memicu ketidakstabilan politik, dan kekerasan etnis dan agama di Indonesia, dan secara langsung menyebabkan lengsernya Presiden Soeharto pada Mei 1998. Di Thailand, tempat krisis dimulai, terjadi perubahan ekonomi besar-besaran yang sangat mempengaruhi politik dan media. Di Malaysia, Perdana Menteri Mahathir Mohamad secara mengejutkan selamat dari krisis, tapi memenjarakan wakilnya, Anwar Ibrahim, dengan tuduhan palsu.
Di Jakarta, pada suatu petang tahun 1999 di sebuah kafe, koresponden BBC Jonathan Head cerita baru saja wawancara Presiden B.J. Habibie dan Habibie setuju dibuat referendum soal status politik Timor Leste. Ini perkembangan luar biasa menarik sesudah Indonesia menduduki Timor Leste sejak 1975.
Namun tahun itu juga awal periode ketika banyak wartawan di Indonesia, termasuk saya, menyaksikan kekerasan sektarian dan komunal berskala besar, yang menewaskan sekitar 90.000 orang. Mulai dari pembunuhan massal terhadap orang Madura di Kalimantan sampai kekerasan sektarian di Kepulauan Maluku plus kekacauan di Timor Leste setelah referendum yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-bangsa.
Media menghadapi banyak tantangan dengan krisis ekonomi Asia Tenggara. Mereka kehilangan iklan, anggaran ruang redaksi berkurang, serta berhadapan situasi politik yang rumit, baik di ibu kota maupun di berbagai provinsi, seperti Papua di Indonesia, ketika gerakan kemerdekaan memicu kekerasan, atau Pontianak dengan kekerasan antar-etnik. Media, seperti banyak bisnis lain, harus bekerja keras. Tapi teman-teman media saya, yang menjadi pelopor kebebasan media di kawasan ini, tetap bertahan.
Dua Puluh Tahun Kemudian
Selama dua dekade terakhir ini, kami jalani kehidupan masing-masing di tempat berbeda. Steven Gan, kembali ke Kuala Lumpur, mendirikan Malaysiakini. Santoso mendirikan jaringan radio KBR, membagikan konten berita jaringannya ke lebih dari 700 stasiun radio di seluruh Indonesia.
Maria Ressa menulis buku tentang jaringan teror Jemaah Islamiyah di Asia Tenggara dari Singapura dengan beasiswa. Dia kemudian mendirikan situs web berita Rappler di Filipina, dan memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian atas keberaniannya dalam membela kebebasan pers. Aung Zaw memindahkan operasi majalah Irrawaddy miliknya, dari Chiang Mai ke Yangon. Kemudian setelah kudeta militer Myanmar pada Februari 2021, memindahkannya kembali ke pengasingan. Di Jakarta, Goenawan Mohamad menerbitkan kembali majalah Tempo. Berbagai organisasi ini berusaha hasilkan jurnalisme yang bermutu. Dan teman-teman saya menjadi wartawan yang meraih berbagai penghargaan.
Aung San Suu Kyi dibebaskan dari tahanan rumahnya di Myanmar, yang mendorong Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengunjungi Yangon pada November 2012. Saat itu, Obama memuji reformasi di Myanmar. Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi memenangkan pemilihan umum 2015.
Namun mulai 2012, naluri sektarian dan rasialis, bukan sesuatu yang baru, muncul lagi di Myanmar, dengan seruan kebencian anti-Muslim menyebar terutama di negara bagian Rakhine, menyasar orang Rohingya dan minoritas Muslim lain. Ujaran kebencian di media sosial memicu serangan terhadap Muslim lainnya di Myanmar tengah dan utara pada 2013. Lalu pada Agustus 2017 dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan genosida oleh militer Myanmar terhadap etnik Rohingya.
Kekerasan di Myanmar juga memperlihatkan cara baru untuk berbagi informasi, tepatnya, informasi berisi kebencian dan kebodohan, yakni lewat media sosial. Di Myanmar, media sosial terpenting adalah Facebook hingga kebodohan dan kebencian ini paling sering disalurkan lewat Facebook.
Perubahan cara orang mencari dan menerima informasi juga jadi tantangan bagi media-media berita di Asia Tenggara.
Google, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan perusahaan media sosial lain menjadi tantangan serius bagi popularitas dan pengaruh media tradisional. Perusahaan-perusahaan teknologi ini mengubah cara orang Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja, dan lainnya di Asia Tenggara, serta di seluruh dunia, dalam mengkonsumsi informasi. Banyak konsumen ini masih perlu belajar membedakan antara berita, yang dibuat dengan verifikasi, versus propaganda, yang dibuat dari berbagai pihak yang punya kepentingan, dan tak sepenuhnya memahami proses riset, pemeriksaan fakta, penulisan, dan tinjauan editorial dari jurnalisme yang bermutu.
Kenyataannya, jurnalis bukan lagi penjaga gawang berita. Mereka kehilangan peran untuk membantu menentukan informasi dan peristiwa apa yang harus sampai ke publik, dan apa yang tidak. Dengan media sosial, setiap orang sekarang menjadi redaktur dan manajer sirkulasi mereka sendiri. Dewan Pers memperkirakan Indonesia sekarang memiliki 47.000 “organisasi media”—sebagian besar hanya situs web berbasis “jurnalis warga.” Angka ini menunjukkan peningkatan luar biasa dari sekitar 1.000 organisasi media formal pada tahun 1998.
Di Indonesia, media sosial juga membantu mengobarkan kebodohan dan kebencian. Intoleransi melanda Indonesia. Minoritas agama termasuk Kristen, Hindu, Buddha, maupun Ahmadiyah dan Syiah, serta penganut agama lokal dan pengikut agama baru seperti Millah Abraham, menghadapi diskriminasi, intimidasi, dan kekerasan. Diskriminasi terhadap perempuan dan LGBT juga meluas.
Teknologi bisa berubah namun kepercayaan—ketika diperoleh dan dipelihara—akan bertahan lama.
Pada Mei 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghukum mantan Gubernur Jakarta, Basuki “Ahok” Purnama, seorang Kristen, dua tahun penjara karena “penodaan agama Islam.” Ahok dituduh menodai agama Islam saat pemilihan gubernur Jakarta. Lebih dari 150 orang dipenjara karena penodaan agama di Indonesia pasca-Soeharto. Peningkatan yang sangat besar dari hanya 10 kasus dalam tiga dekade.
Reporters Without Borders, sebuah organisasi pemantau kebebasan pers di Prancis, sejak 2002 menerbitkan indeks kebebasan pers di seluruh dunia, dan selama dua dekade terakhir, setiap tahun mencatat penurunan kebebasan pers di Asia Tenggara.
Pada 2022, Myanmar tetap yang terburuk dari sebelas negara di kawasan ini. Menariknya, Timor Leste, negara-bangsa paling muda, adalah negara yang paling bebas, bahkan tak memiliki pasal pidana pencemaran, meskipun, seperti yang berulang kali dikeluhkan Presiden Jose Ramos-Horta, masih hadapi kesulitan untuk bergabung dengan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (Association of South East Asian Nations, ASEAN). Secara umum, sepuluh negara lainnya menjadi lebih buruk termasuk Laos, negara dengan kediktatoran partai tunggal, yang entah kenapa, tak diperhitungkan oleh Reporters Without Borders.
Thailand, yang tak seperti negara-negara lain di kawasan ini, tak pernah mengalami kolonialisme Barat, turun dari urutan ke-66 pada 2002 menjadi ke-115 pada 2022. Artinya? Thailand tak serta-merta memiliki infrastruktur hukum yang lebih baik dari negara-negara bekas koloni Eropa seperti Malaysia, Filipina, atau Vietnam, yang memakai sistem hukum ala Uni Soviet.
Thailand masih mempertahankan hukum lese majeste “untuk melindungi” monarki, termasuk raja, ratu, putra mahkota, dan wali—dari pencemaran nama baik. Hukumannya, tiga sampai 15 tahun penjara untuk setiap pelanggaran, dan mereka yang dituduh selalu berada dalam penahanan yang lama.
Peringkat kebebasan pers di Asia Tenggara tahun 2002 dan 2022
|
Negara |
Peringkat pada 2002 dari 139 negara |
Peringkat pada 2022 dari 180 negara |
|
Timor Leste |
- |
17 |
|
Malaysia |
110 |
113 |
|
Thailand |
66 |
115 |
|
Indonesia |
57 |
117 |
|
Singapura |
- |
139 |
|
Kamboja |
71 |
142 |
|
Brunei |
111 |
144 |
|
Filipina |
90 |
147 |
|
Vietnam |
131 |
174 |
|
Myanmar |
137 |
176 |
SUMBER: SURVEI REPORTERS WITHOUT BORDERS PADA 2002 DAN 2022
Jadi mengapa kebebasan pers, dan juga demokrasi, tak menguat di Asia Tenggara seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi?
Peringkat Filipina turun drastis dari nomor 90 pada 2002 menjadi peringkat 147 pada 2022. Indonesia masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, seorang pejuang demokrasi, mencapai peringkat ke-57 pada 2002. Sekarang, Indonesia berada pada peringkat 117.
Sistem politik dan tradisi winner take all, yang lazim di kawasan ini, tentu saja merupakan satu faktor. Thailand mengalami apa yang disebut persaingan Kaos Merah versus Kaos Kuning sejak 2006 dengan serentetan kekerasan. Pada 2014, Panglima Angkatan Darat Prayut Chan-o-cha melakukan kudeta setelah satu dekade persaingan ini.
Di Singapura, People’s Action Party pimpinan Perdana Menteri Lee Hsien Loong, yang terus memerintah negara itu sejak perpisahan pahit dari Malaysia pada 1965, memiliki peraturan yang memungkinkan pemerintah untuk langsung menunjuk editor dan redaksi perusahaan media terkemuka.
Di Malaysia, status dan kegiatan sembilan kesultanan Melayu di Semenanjung Malaka adalah masalah peka bahkan sakral. Segala komentar yang dianggap kritis terhadap kesultanan dapat mengakibatkan tuntutan dan hukuman berat. Ia mendorong swasensor. Politisi biasa pakai peraturan untuk membatasi kerja wartawan.
Di Kamboja, transisi demokrasi, sejak 1992 dengan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, memungkinkan munculnya pers yang bermutu. Ia berakhir ketika Perdana Menteri Hun Sen bikin gerakan buat menindas para wartawan. Peringkat Kamboja turun dari 71 pada 2002 menjadi 142 pada 2022.
Kudeta adalah faktor paling merusak kebebasan pers. Banyak negara di Asia Tenggara akrab dengan kudeta. Militer Myanmar melakukan kudeta pada Februari 2021. Ia mengakibatkan meluasnya kekerasan terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta, bersamaan dengan tekanan besar-besaran terhadap jurnalis.
“Ketika kudeta terjadi, industri media Myanmar terjerembab masuk jurang kegelapan,” ujar seorang wartawan Myanmar pada pembukaan film, “Walking Through the Darkness.” Film ini cerita bagaimana jurnalis Myanmar melarikan diri dari kota-kota setelah kudeta dan bekerja di daerah-daerah yang dikuasai organisasi-organisasi etnis atau di pengasingan di Thailand, untuk tetap bekerja, menulis dan mengeluarkan berita.
“Penguasa militer, boleh suka, boleh tidak suka, kepada pekerjaan kami, namun jurnalisme diperlukan masyarakat, perannya sangat penting,” kata jurnalis lainnya. “Jurnalis harus bisa tetap lakukan pekerjaan.”
Tampaknya, beberapa tokoh dunia, termasuk Barack Obama, terlalu optimistis dengan masa depan Myanmar. Terutama, daya tahan pemerintahan demokratis dan kebebasan pers di Myanmar, ketika mereka berhadapan dengan junta militer, yang kerap melanggar hak asasi manusia, dan percaya militer ditakdirkan untuk memegang kekuasaan.
Namun, beberapa negara menunjukkan kemajuan. Malaysia memilih pemerintahan reformis untuk periode dua tahun, yang umurnya singkat, namun berhasil menjebloskan mantan perdana menteri Najib Razak ke penjara karena korupsi.
Asia Tenggara selama berabad-abad selalu menjadi kawasan di mana persaingan global bergesekan. Ketika kekuasaan yang jauh lebih besar menegaskan pengaruhnya, dari berbagai kesultanan Islam di Timur Tengah hingga berbagai dinasti di Tiongkok, dari kekuatan Eropa hingga pengaruh India. Kini, Asia Tenggara adalah ajang persaingan dua ekonomi terbesar di dunia: Amerika Serikat dan Tiongkok. Laut Cina Selatan merupakan titik panas persaingan Tiongkok dan Amerika Serikat.
Tiongkok membuat takut jurnalis Hong Kong dengan tindakan represif. Tak mengherankan kalau peringkat Reporters Without Borders untuk Hong Kong, sebagai negara dengan peringkat terbaik ke-18 pada 2002, kini turun ke peringkat ke-148 dari 180 negara.
Presiden Tiongkok, Xi Jinping, rupanya belum mengetahui bahwa dalam jangka panjang, kebebasan pers punya kaitan dengan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik.
Polisi Hong Kong menangkap Jimmy Lai dari Apple Daily pada Desember 2021. Dakwaannya, mengada-ngada. Penangkapan Jimmy Lai adalah simbol merosotnya kebebasan pers di Hong Kong.
Saya ingat Jimmy Lai menjabat tangan saya pada pertemuan 1995. Dia menyampaikan salam kepada teman-teman saya di Jakarta, yang baru saja mendirikan Aliansi Jurnalis Independen dan memperjuangkan kebebasan media di Indonesia.
Infrastruktur hukum memainkan peran penting dalam membatasi kebebasan pers di Asia Tenggara. Di Indonesia, pelecehan, diskriminasi, dan kekerasan terhadap minoritas agama, gender maupun seksualitas, difasilitasi oleh infrastruktur hukum. Misalnya, pada 2006, pemerintah mengeluarkan aturan dengan istilah “kerukunan umat beragama.” Praktiknya, aturan ini membuat “mayoritas” punya hak veto terhadap “minoritas.” Ia membuat ribuan rumah ibadah diganggu, ditutup, bahkan dibakar, paling banyak tentu saja gereja-gereja Kristen—sebagai minoritas paling besar di Indonesia. Banyak wartawan Indonesia sulit memisahkan agama dan profesinya—sama dengan Myanmar.
Di Vietnam, Partai Komunis Vietnam monopoli kekuasaan politik dan tak membolehkan siapa pun menentang para tokoh partai. Hak-hak dasar, termasuk kebebasan berbicara, berpendapat, pers, berserikat, dan beragama, dibatasi. Aktivis hak asasi manusia dan blogger menghadapi pelecehan, intimidasi, penyerangan fisik, dan penjara.
Negara Vietnam mengontrol semua media. Partai Komunis membuat media menjadi “suara partai, organ negara, dan organisasi sosial.” Departemen propaganda milik Partai Komunis Vietnam rapat setiap minggu di Hanoi untuk memastikan bahwa tak ada hal yang tak mereka sukai muncul di media. Hakim-hakim pengadilan, yang dikontrol partai, menghukum penjara banyak jurnalis independen, termasuk Pham Doan Trang, Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy, dan lainnya.
Laos juga dikuasai partai komunis. Di Laos, tak mungkin untuk wartawan menjalankan media independent. Pemerintah menindak keras organisasi atau individu yang berani mengkritik Partai Revolusioner Rakyat Laos maupun pemerintah. Buruh migran, yang mengkritik pemerintah Laos saat mereka bekerja di Thailand, bisa ditangkap dan dihukum 15-20 tahun penjara ketika kembali ke Laos.
Di Singapura, dua grup media memiliki hampir semua media cetak, radio, dan televisi. MediaCorp perusahaan negara. Singapore Press Holdings, seharusnya dimiliki beberapa orang, tapi direksinya ditunjuk pemerintah. Menariknya, New Naratif, sebuah media alternatif, muncul dari Singapura tapi sudah dapat gangguan. The Online Citizen, media alternatif lain di Singapura, sudah tutup lewat tuntutan hukum sehingga pindahkan badan hukum mereka ke Taiwan.
Di Manila, Presiden Rodrigo Duterte menutup ABS-CBN, jaringan televisi terbesar kedua di Filipina, pada 2020. Untungnya, ABS-CBN terus siaran secara daring. Berbagai kasus hukum terhadap Maria Ressa dan rekan-rekannya di Rappler tampaknya dipakai untuk menutup situs berita tersebut. Kini belum ada tanda-tanda bahwa keadaan akan menjadi lebih baik di bawah presiden baru, Ferdinand Marcos Jr., putra mendiang diktator Filipina.
Konteks sosial budaya menciptakan banyak hambatan. Di Malaysia, media berbahasa Melayu, yang dibaca oleh mayoritas warga Malaysia, sering dikenakan sensor melebihi rekan-rekan mereka yang berbahasa Inggris, Mandarin atau Tamil.
Di Malaysia dan Indonesia yang mayoritas Muslim, isu-isu yang berhubungan dengan Islam seperti pindah agama, wajib jilbab, pernikahan anak, dan penodaan agama, merupakan hal tabu hingga saat ini. Menariknya, media Indonesia makin giat meliput kekerasan seksual dan kejahatan lainnya di pesantren dan sekolah agama.
Sayangnya, banyak media Indonesia memberikan banyak kelonggaran dengan tak meliput secara teratur bagaimana peraturan berbagai daerah, atas nama syariah Islam, membatasi hak asasi manusia. Kini Indonesia memiliki lebih dari 700 peraturan, dibuat atas nama Syariat Islam, yang mendiskriminasi minoritas agama, gender—termasuk aturan wajib jilba—dan seksualitas. Ini belum termasuk pasal-pasal karet di Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan berbagai hukum lain.
Pedoman bagi wartawan Indonesia seyogyanya UUD 1945. Ia tersurat menjamin kebebasan beragama, hak berserikat, mengeluarkan pendapat dan hak asasi manusia. Indonesia, dan negara-negara lain di Asia Tenggara, seyogianya menghapus pasal-pasal karet yang dipakai buat pidana pencemaran. Sepuluh negara Asia Tenggara ini perlu belajar dari Timor Leste.
Saya kira penting diketahui bahwa semua negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sudah ratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Berbagai konvensi internasional ini memberikan pedoman internasional yang seyogianya diikuti wartawan buat mencari kebenaran fungsional. Standar international ini jauh lebih baik daripada kebanyakan hukum nasional, misalnya, soal pidana pencemaran di negara masing-masing.
Saya jadi mengerti setelah bekerja di Bangkok, Kuala Lumpur, Phnom Penh dan Jakarta, bahwa Asia Tenggara adalah kawasan rumit yang sangat beragam, secara bahasa, ras, agama, budaya dan sejarah. Di kawasan ini ada negara mayoritas Muslim seperti Brunei, Malaysia, dan Indonesia. Ada juga negara mayoritas Buddha seperti Kamboja, Myanmar dan Thailand. Filipina dan Timor Leste adalah negara mayoritas beragama Kristen. Ada juga negara komunis seperti Laos dan Vietnam.
Asia Tenggara, beda dengan Afrika dan Amerika Latin, secara tradisional tak memiliki bahasa kolonial yang dapat digunakan negara-negara itu untuk berkomunikasi satu sama lain. Malaysia, Singapura, Myanmar, dan Brunei bekas koloni dengan bahasa Inggris. Vietnam, Laos dan Kamboja punya bahasa Perancis. Indonesia, tentu saja, punya banyak dokumentasi dalam bahasa Belanda. Orang-orang di Asia Tenggara sulit komunikasi satu dengan yang lain karena tak punya bahasa yang dimiliki bersama.
Saya bangga ketika pada Desember 2021, Maria Ressa mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian di Oslo, bersama jurnalis Rusia Dmitry Muratov.
Kedua wartawan ini tidak naif. Mereka mengerti bahwa Hadiah Nobel takkan mengubah situasi di negara masing-masing. Muratov menutup sendiri surat kabar Novaya Gazeta miliknya setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Muratov sadar bahwa aturan baru di Rusia membuat awak redaksinya bisa jadi masuk penjara. Maria Ressa masih berhadapan dengan dakwaan dari kasus-kasus buatan Presiden Duterte serta antek-anteknya.
Saat menerima Nobel, Maria Ressa memberikan pidato di Oslo, “Tanpa fakta, Anda takkan mendapatkan kebenaran. Tanpa kebenaran, Anda takkan mendapatkan kepercayaan. Tanpa kepercayaan, kita takkan bisa memiliki realitas bersama, takkan ada demokrasi, dan menjadi mustahil menangani tantangan kemanusiaan zaman ini: perubahan iklim, virus corona, dan sekarang, perjuangan demi kebenaran.”
Ressa menyerukan dukungan yang lebih besar untuk jurnalisme independen, untuk perlindungan jurnalis, dan meminta pertanggungjawaban dari negara-negara yang memberangus wartawan.
Di Jakarta, saya sering mengatakan makin bermutu jurnalisme, makin bermutu masyarakat. Sebaliknya, makin tidak bermutu jurnalisme, makin tidak bermutu masyarakat.
Pesan ini sangat jelas. Kalangan bangsawan, pengusaha, ulama, kepala suku, pejabat pemerintah, jenderal, dan tokoh masyarakat sipil di Asia Tenggara seyogianya mengerti bahwa mutu masyarakat ditentukan oleh mutu jurnalisme. Dua dekade sudah berlalu sejak krisis ekonomi Asia, dan kesimpulan soal pentingnya kebebasan pers semakin jelas. Asia Tenggara harus memajukan kebebasan pers dan menghapus semua pasal karet bila tak mau mengulangi moral hazard pada 1997.
Ini adalah satu-satunya jalan untuk maju.
Makalah ini dipresentasikan dalam Bahasa Inggris pada Deutscher Orientalistentag ke-34 yang diadakan di Free University Berlin pada 15 September 2022. Edisi Bahasa Inggris diterbitkan Human Rights Watch dengan judul, “The Rocky Road to Press Freedom in South East Asia.”