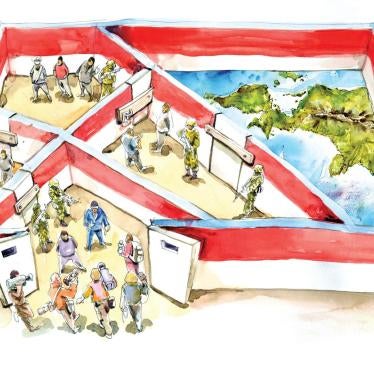(New York) - Pemerintah Bangladesh seharusnya meninjau kembali dan mereformasi usulan Undang-Undang Keamanan Digital (DSA) ketimbang menetapkan undang-undang itu dalam bentuknya saat ini, kata Human Rights Watch hari ini (22/2).
Pada 29 Januari 2018, kabinet menyetujui rancangan undang-undang, yang dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) yang banyak dikritik. Rancangan ini bahkan lebih luas daripada undang-undang yang ingin diganti dan melanggar kewajiban internasional negara itu untuk melindungi kebebasan berbicara.
“Undang-undang yang diusulkan itu benar-benar melemahkan pernyataan pemerintah bahwa mereka tak berniat membatasi hak kebebasan berbicara,” kata Brad Adams, direktur Asia. “Dengan setidaknya lima ketentuan berbeda yang memberikan hukuman pidana jenis ujaran yang didefinisikan secara samar, undang-undang tersebut ini adalah tak ubahnya izin yang digunakan secara luas untuk menekan suara-suara kritis.”
Setelah pelanggaran berulang atas Pasal 57 Undang-Undang ICT untuk mengadili para jurnalis dan kalangan lain karena mengkritik perdana menteri, keluarganya, atau pemerintahannya di media sosial, pemerintah Bangladesh berkomitmen untuk mencabut undang-undang tersebut. Meski undang-undang baru yang diusulkan untuk menggantikan Undang-undang ICT membatasi penuntutan karena penghinaan terhadap orang-orang yang dapat diadili berdasarkan hukum pidana dan menetapkan persyaratan yang pasti untuk pelanggaran tertentu, namun undang-undang tersebut bahkan lebih kejam daripada yang ada di pasal 57.
Pasal 14 dari rancangan tersebut akan menjatuhkan hukuman penjara hingga 14 tahun karena menyebarkan “propaganda dan kampanye terhadap perang pembebasan Bangladesh atau semangat perang pembebasan atau Bapak Bangsa.” Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga ahli independen yang memantau kepatuhan terhadap Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), di mana Bangladesh menjadi bagiannya, telah secara tegas menyatakan bahwa undang-undang yang menjatuhkan hukuman pidana atas ekspresi berpendapat tentang fakta sejarah bertentangan dengan kewajiban negara untuk menghormati kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Pasal 25(a) akan memungkinkan hukuman sampai tiga tahun penjara karena menerbitkan informasi yang “agresif atau menakutkan” – istilah umum yang tak dijelaskan dalam usulan undang-undang. Penggunaan istilah tidak jelas semacam ini melanggar persyaratan bahwa undang-undang yang membatasi ujaran harus dirumuskan dengan ketepatan memadai, guna menjelaskan ujaran mana yang akan melanggar hukum. Ketidakjelasan dalam pelanggaran ini, ditambah kejamnya potensi hukuman, meningkatkan kemungkinan sensor pribadi untuk menghindari kemungkinan penuntutan.
Pasal 31, yang akan menjatuhkan hukuman penjara hingga 10 tahun karena mengunggah informasi yang “merusak keharmonisan komunal atau menciptakan ketidakstabilan atau kekacauan atau mengganggu atau akan mengganggu situasi hukum dan ketertiban,” juga sama cacatnya. Tanpa definisi jelas tentang ucapan apa yang dianggap “merusak keharmonisan komunal” atau “menciptakan ketidakstabilan,” undang-undang itu memberi kesempatan luas bagi pemerintah untuk menggunakannya untuk menuntut ujaran yang tidak disukai.
Hampir semua kritik pemerintah bisa berujung pada ketidakpuasan dan kemungkinan demonstrasi publik. Pemerintah seharusnya tidak bisa menghukum kritik dengan alasan bahwa hal itu mungkin “mengganggu situasi hukum dan ketertiban.”
Pasal 31 juga mencakup ujaran yang “menciptakan permusuhan, kebencian atau antipati di antara berbagai kelas dan masyarakat.” Meski tujuan untuk mencegah pertengkaran antarkomunal adalah hal yang penting, hal itu seharusnya dilakukan dengan cara yang sesedikit mungkin membatasi ujaran. Ahli hak asasi manusia PBB telah menyatakan bahwa:
Mutlak diperlukan dalam sebuah masyarakat bebas, pembatasan debat publik atau wacana dan perlindungan terhadap keharmonisan rasial dilakukan dengan tidak merugikan hak asasi manusia, seperti kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul.
Definisi mengenai “ujaran kebencian” dalam undang-undang yang terlalu luas membuka pintu bagi diterapkannya hukum yang sewenang-wenang dan tidak adil, serta menciptakan suasana mengkhawatirkan dalam diskusi mengenai isu-isu terkait ras dan agama.
Pasal 29, seperti Pasal 57 dari Undang-Undang ICT, mengkriminalkan penghinaan di dunia maya. Meski Pasal 29, tidak seperti Undang-Undang ICT, membatasi tuduhan penghinaan bagi mereka yang memenuhi ketentuan pidana penghinaan dalam hukum pidana, namun demikian bertentangan dengan pengakuan yang berkembang bahwa penghinaan semestinya dianggap sebagai masalah perdata, bukan kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman penjara.
Pasal 28 akan memberlakukan hukuman lima tahun penjara karena ujaran yang “melukai perasaan keagamaan. ”Meskipun ketentuan ini, tidak seperti pasal 57 ICT, ini memerlukan maksud, penambahan tersebut tidak cukup untuk membuatnya sesuai dengan norma internasional. Sebagaimana dicatat dalam contoh kasus Handyside yang berpengaruh, kebebasan berekspresi tak hanya berlaku untuk informasi atau gagasan “yang diterima dengan baik atau dianggap tidak menganggu atau sebagai masalah ketidakpedulian, tetapi juga terhadap pihak yang menyinggung, mengejutkan atau menggganggu Negara atau lapisan masyarakat.” Larangan ujaran yang melukai perasaan keagamaan seseorang, diperkuat dengan hukuman kriminal, tak dapat dibenarkan sebagai pembatasan yang diperlukan dan proporsional terhadap ujaran.
“Undang-Undang Keamanan Digital ini sama sekali tidak konsisten dengan kewajiban Bangladesh untuk melindungi kebebasan berbicara,” kata Adams. “Parlemen semestinya menolak undang-undang ini dan mendesakkan sebuah undang-undang yang benar-benar menghormati hak warga negara untuk berbicara secara bebas.”