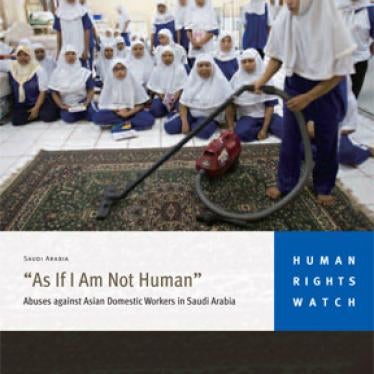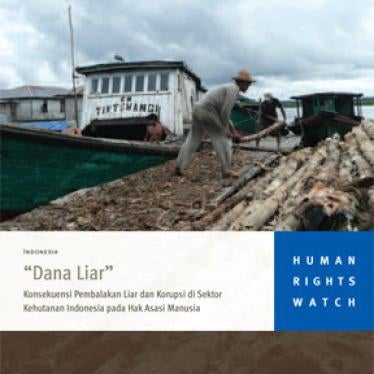(Beirut) – Menurut laporan Human Rights Watch yang diterbitkan hari ini, sejumlah ulama dan institusi negara Saudi telah menyulut kebencian dan diskriminasi terhadap sejumlah kalangan minoritas agama, termasuk warga muslim Syiah.
Laporan setebal 62 halaman berjudul “‘Mereka Bukan Saudara Kami’: Ujaran Kebencian oleh Pejabat Negara Arab Saudi”, dokumen yang membiarkan para cendekiawan agama dan ulama yang berada di bawah naungan pemerintah, untuk menyebut warga beragama minoritas dengan istilah menghina atau mendemonisasi mereka dalam berbagai dokumen resmi dan peraturan keagamaan. Istilah yang digunakan akan memengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah. Dalam beberapa tahun belakangan, ulama pemerintah dan beberapa pihak lain telah menggunakan internet pun media sosial untuk menyulut kebencian terhadap warga Syiah, serta kelompok-kelompok lain yang dianggap tidak mematuhi pandangan pemerintah Saudi.
“Arab Saudi telah mendorong wacana reformasi selama beberapa tahun belakangan, tapi mereka tetap membiarkan banyak buku pelajaran, dan para ulama yang berafiliasi dengan pemerintah, secara terang-terangan mengutuk warga minoritas seperti pemeluk Syiah,” kata Sarah Leah Whitson, Direktur Timur Tengah di Human Rights Watch. “Ujaran kebencian ini memperpanjang diskriminasi sistematis terhadap minoritas Syiah, dan pada praktik terburuknya, digunakan sebagai alasan kelompok pro-kekerasan untuk menyerang mereka,”
Human Rights Watch mencatat bahwa hasutan sekaligus bias anti-Syiah di sistem peradilan, dan kurikulum pelajaran agama Kementerian Pendidikan Arab Saudi, telah menjadi alat penting untuk memaksakan diskriminasi terhadap warga Syiah di negara ini. Human Rights Watch baru-baru ini mencatat sejumlah ujaran bernada menghina bagi agama-agama lain seperti Yahudi, Kristen dan mazhab Sufi dalam kurikulum pendidikan agama Arab Saudi.
Ulama pemerintah, semuanya penganut mazhab Sunni, seringkali menyebut para penganut Syiah sebagai rafidha atau rawafidh (golongan penolak), dan menempelkan stigma negatif terhadap kepercayaan serta ritual keagamaan mereka. Para ulama ini juga mengecam praktik perkawinan dan pergaulan antarmazhab. Salah seorang anggota Dewan Ulama Senior, institusi keagamaan tertinggi di Arab Saudi, menyatakan bahwa Syiah “bukan saudara kami… mereka itu saudara Setan…”, dalam sebuah acara publik.
Ujaran kebencian seperti ini dapat berakibat fatal saat digunakan oleh kelompok bersenjata seperti ISIS atau Al-Qaeda untuk membenarkan penyerangan terhadap warga Syiah. Sejak pertengahan 2015, ISIS sudah menyerang enam masjid Syiah dan tempat ibadah lainnya di Propinsi Timur dan Najran, yang menewaskan lebih dari 40 orang. Siaran pers ISIS mengklaim beberapa penyerangan itu menyasar “pelaku syirik” (politeis) dan rafidha (golongan penolak), istilah yang digunakan dalam buku pelajaran Arab Saudi untuk mengincar penganut Syiah.
Abdulaziz Bin Baz, mantan mufti besar Arab Saudi yang meninggal dunia pada 1999, mengutuk warga Syiah di beberapa putusan fatwa. Tulisan dan fatwa Bin Baz hingga kini masih bisa diakses secara umum di situs resmi Komite Permanen untuk Riset Islam dan Pemutusan Fatwa Arab Saudi.
Beberapa pernyataan ulama tersebut mengesankan bahwa warga Syiah adalah bagian dari persekongkolan melawan negara, pasukan kelima dalam negeri untuk Iran, dan sejak awal sudah tidak setia. Pemerintah Arab Saudi juga membiarkan ulama yang memiliki pengikut masif di media sosial – beberapa dalam jutaan – dan media untuk memberi stigma pada warga Syiah dengan kekebalan.
Bias anti-Syiah ini menjalar hingga ke dalam sistem peradilan Arab Saudi, yang dikendalikan oleh kelompok agama berpengaruh, dan kerap memperlakukan warga Syiah secara diskriminatif atau mengkriminalisasi praktik keagamaan mereka dengan sewenang-wenang. Contohnya, pada 2015 pengadilan Arab Saudi menjatuhkan vonis dua bulan penjara dan 60 kali cambukan bagi seorang Syiah, karena ia menggelar salat berjamaah untuk penganut Syiah secara tertutup di rumah ayahnya. Pada 2014, pengadilan lain di Arab Saudi juga menghukum seorang pria Sunni karena “duduk bersebelahan dengan seorang dari kelompok Syiah”.
Kurikulum Kementerian Pendidikan Arab Saudi mengajarkan al-tawhid (monoteisme) di tingkat sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas, dengan bahasa tersirat untuk memberi stigma pada praktik keagamaan Syiah sebagai perilaku syirik atau ghulah (berlebihan). Buku pelajaran agama Arab Saudi mengkritik ritual ziarah Syiah dan Sufi ke makam, tempat-tempat yang dianggap keramat, serta tawassul (berdoa melalui perantara), sebagai ritual untuk memanggil nabi atau anggota keluarganya sebagai perantara menuju Tuhan. Buku-buku pelajaran agama terbitan pemerintah menyatakan sejumlah ritual ini, yang dipahami warga Sunni dan Syiah sebagai Syiah, merupakan dasar untuk dihapus dari Islam, dihukum dengan menghuni neraka selamanya.
Hukum hak asasi manusia internasional mengharuskan pemerintah di manapun untuk melarang “setiap anjuran kebencian berbasis bangsa, ras, atau agama yang termasuk dalam hasutan dikriminasi, kebencian atau kekerasan.” Implementasi dari peraturan ini tidak dilakukan secara adil, bahkan beberapa kali digunakan sebagai dalih untuk membatasi kebebasan berbicara atau mengincar kelompok-kelompok minoritas. Setiap langkah untuk melawan ujaran kebencian seharusnya dilakukan dalam jaminan kebebasan berekspresi.
Guna mengatasi persoalan ini, beberapa tahun belakangan para ahli telah mengajukan tes untuk menentukan apakah suatu jenis ujaran bisa dibatasi secara hukum. Berdasarkan formula itu, catatan Human Rights Watch menunjukkan bahwa ceramah yang dilakukan ulama dan cendekiawan Arab Saudi seringkali melewati batas ujaran kebencian, menghasut kebencian atau diskriminasi. Beberapa pernyataan lain tidak melewati batas tersebut, tapi pemerintah Arab Saudi seharusnya menolak dan menetralisir ujaran tersebut di hadapan publik. Mengingat besarnya pengaruh dan jangkauan para cendekiawan ini, pernyataan mereka menggenjot sistem diskriminasi terhadap warga Syiah.
Pemerintah Arab Saudi seharusnya memerintahkan ujaran kebencian oleh para ulama negara dan institusi pemerintah untuk segera dihentikan.
Komisi Amerika Serikat Untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF) telah berulang kali menggolongkan Arab Saudi sebagai sebuah “negara yang menjadi perhatian khusus”, sebutan paling keras bagi negara yang melanggar kebebasan beragama. Kesepakatan Kebebasan Agama Internasional tahun 1998 membolehkan Presiden Amerika Serikat untuk menerbitkan surat pengabaian jika dianggap bisa “memajukan maksud yang dituju” atas kesepakatan tersebut, atau jika “kepentingan nasional Amerika Serikat memerlukan penerbitan surat pengabaian.” Presiden Amerika Serikat sudah menerbitkan surat pengabaian macam itu pada Arab Saudi sejak 2006.
Pemerintah Amerika Serikat seharusnya mencabut surat itu dan mulai bekerjasama dengan pemerintah Arab Saudi, guna menghentikan hasutan kebencian atau diskriminasi terhadap warga Syiah, Sufi serta agama-agama lain. Pemerintah Amerika Serikat juga semestinya bersikeras untuk menghilangkan kritik dan stigmatisasi terhadap ritual keagamaan warga Syiah, Sufi, dan agama-agama lainnya dari kurikulum pendidikan agama Arab Saudi.
“Meskipun Arab Saudi masih memiliki catatan buruk dalam kebebasan beragama, Amerika Serikat telah melindungi Arab Saudi dari kemungkinan penjatuhan sanksi menurut hukum Amerika Serikat,” kata Whitson. “Pemerintah Amerika Serikat seharusnya mengimplementasikan undang-undangnya sendiri agar Arab Saudi, sebagai sekutu, bisa dimintai pertanggungjawaban.”