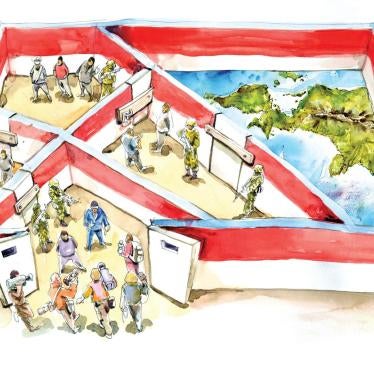Ada beberapa bahaya baru bagi jurnalis asing yang mencoba meliput di dua provinsi paling timur Indonesia, Papua dan Papua Barat (secara umum disebut “Papua”): penolakan visa dan dimasukkan dalam daftar hitam. Tanyakan saja pada koresponden France 24 TV yang berbasis di Bangkok, Cyril Payen.
Pada 8 Januari, Kedutaan Besar Indonesia di Bangkok memberitahu Payen bahwa pengajuan visa jurnalisnya untuk meliput di Papua ditolak. Penolakan tersebut tidak sepenuhnya mengejutkan. Pada 8 November, pejabat Kementerian Luar Negeri Indonesia memberitahu Kedutaan Besar Prancis di Jakarta bahwa mereka menganggap liputan Payen sebelumnya, yang berfokus pada sentimen pro-kemerdekaan di provinsi tersebut, “bias dan tak berimbang.” Alih-alih berkorespondensi dengan Payen dan France 24 untuk secara terbuka menguji laporan yang diduga tidak akurat, pemerintah Indonesia mengambil langkah yang menghukum dan tidak proporsional, yaitu mengancam penolakan visa untuk periode tertentu bagi seluruh wartawan France 24 yang ingin meliput dari Indonesia.
Kesulitan yang dihadapi Payen menggarisbawahi celah yang terlihat jelas antara retorika Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo, yang telah mengumumkan “membuka” Papua dan Papua Barat (secara umum disebut “Papua”) bagi media asing serta realita muram bagi para wartawan yang masih dilarang meliput dari sana.
Tindakan balasan resmi atas liputan soal Papua yang tidak menyenangkan pemerintah tak ubahnya sebuah ancaman bagi para wartawan dan narasumber mereka.
Sepekan setelah Marie Dhumieres, wartawan Prancis yang bertugas Jakarta, pulang dari Papua pada Oktober, kepolisian menahan seorang aktivis Papua yang berpergian dengan Marie dan kedua temannya. Petugas kepolisian menginterogasi ketiga orang tersebut selama 10 jam, menuntut rincian kunjungan Dhumieres. Kepolisian kemudian membebaskan mereka tanpa tuntutan apapun. Dhumieres mengungkapkan kecemasannya dalam sebuah twit untuk Jokowi: “So Mr @jokowi, foreign journalists are free to work anywhere in Papua but the people we interview get arrested after we leave?”
(“Jadi, Pak @jokowi, jurnalis asing dibebaskan bekerja di Papua tapi orang-orang yang kami wawancarai ditangkap setelah kami pergi?”)
Seharusnya hal ini tak terjadi.
Lagipula, pada Mei lalu, Jokowi mengumumkan penghapusan pelarangan de facto yang telah berlaku 25 tahun bagi media asing untuk mengakses Papua. Perubahan kebijakan tersebut seharusnya dapat mengakhiri kecemasan wartawan asing dari segi hukum, melalui penolakan izin pemberitaan dari Papua atau pengabaian pemberian izin tersebut.
Namun pengalaman Payen dan Dhumieres menyorot pemisahan tersebut, yang didokumentasikan pada November 2015 dalam laporan Human Rights Watch antara tujuan kebijakan Jokowi dan tentangan keras dari sejumlah unsur dalam pemerintah Indonesia dan pasukan keamanan untuk membuka Papua bagi media asing.
Sejak pengumuman Jokowi itu, serangkaian pejabat senior pemerintahan telah secara terbuka menyanggah perubahan kebijakan tersebut. Di antara mereka bisa disebut juru bicara Polri dan Brigadir Jenderal Polisi Agus Rianto. Pada 12 Mei, ia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap membatasi akses koresponden asing ke Papua, lewat sistem izin masuk. Rianto membenarkan adanya kebutuhan untuk membatasi akses ke Papua karena perlu mencegah media asing untuk berbicara dengan “orang-orang yang melawan pemerintah” dan untuk memblokir akses “teroris” yang mungkin berpura-pura menjadi jurnalis demi bisa masuk ke Papua.
Pada 26 Mei, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memperingatkan bahwa akses media asing ke Papua memiliki persyaratan, yaitu kewajiban menerbitkan “laporan-laporan yang baik.” Ryacudu tidak secara rinci mendefinisikan “laporan-laporan yang baik,” namun ia secara eksplisit menyamakan laporan negatif para jurnalis asing soal Papua dengan “hasutan” dan mengancam akan mengusir para jurnalis asing manapun yang liputannya tidak menyenangkan pemerintah.
Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan persepsi yang mendarah daging di kalangan pejabat pemerintah Indonesia dan pejabat badan keamanan, bahwa akses media asing ke Papua adalah cikal bakal ketidakstabilan wilayah yang sudah bermasalah dengan meluasnya ketidakpuasan publik dengan Jakarta dan gerakan kemerdekaan yang bersenjata, kecil namun persisten. Tantangan-tantangan bagi kebebasan media di Papua adalah kumpulan kesulitan yang dihadapi oleh para jurnalis Indonesia—terutama yang berasal dari etnis Papua. Jurnalis lokal yang memberitakan topik-topik sensitif politis dan pelanggaran hak asasi manusia seringkali menjadi sasaran pelecehan, intimidasi, dan kekerasan oleh para pejabat, anggota masyarakat dan gerakan pro-kemerdekaan. Percakapan dengan birokrat Indonesia dan pejabat pemerintahan soal tetap adanya hambatan resmi terhadap akses Papua secara rutin merujuk pada Timor Timur dan kecurigaan yang terus ada bahwa keberadaan media asing dan aktivis hak asasi manusia di Timor Timur membantu melapangkan jalan bagi kemerdekaan provinsi tersebut pada 2002.
Tentu, hambatan pemerintah terhadap akses ke Papua lebih luas dari para wartawan. Pasukan keamanan dengan ketat mengawasi aktivitas kelompok-kelompok internasional yang diizinkan pemerintah untuk bekerja di Papua—mereka yang berupaya menunjukkan keprihatinan soal hak asasi manusia mendapatkan pengawasan melekat. Lembaga non-pemerintah internasional seperti kelompok pembangunan asal Belanda, Cordaid, yang menurut pemerintah terlibat dalam “kegiatan politik” dipaksa menghentikan operasinya, dan perwakilan mereka dilarang mengunjungi wilayah tersebut.
Larangan pemerintah terhadap warga asing telah menjangkau para pejabat pejabat PBB dan akademisi, yang dipersepsikan punya rasa permusuhan. Pada 2013 pemerintah menolak izin kunjungan Frank La Rue, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk kebebasan berekspresi, karena dirinya bersikeras ingin mengunjungi Papua dalam rangkaian kunjungannya ke Indonesia. Sejumlah akademisi asing yang sudah mendapatkan izin mengunjungi wilayah ini telah menjadi sasaran pengintaian oleh pasukan keamanan. Mereka yang dianggap bersimpati pada gerakan pro-kemerdekaan telah dimasukkan ke dalam daftar hitam visa.
Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, pada 11 November mengatakan pihaknya akan mengambil tindakan jika ada yang memberi bukti bahwa pemerintah atau pasukan keamanan menghalangi wartawan asing masuk ke Papua. “Coba kembali ke saya, dan kalau perlu, akan kami pecat mereka yang menghalangi,” ujarnya.
Apa yang dialami oleh Cyril Payen, Marie Dhumieres dan jurnalis asing lainnya menyiratkan bahwa ini adalah saatnya Luhut Pandjaitan menepati janji itu.