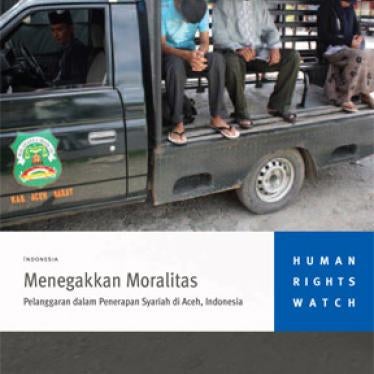|
News Release
Indonesia: Kriminalisasi terhadap Komunitas Gafatar
Ribuan Diusir Paksa, Direlokasi, dan Ditahan
(Jakarta) – Pemerintah Indonesia, pejabat sipil maupun aparat keamanan, ikut terlibat dalam penggusuran lebih dari 7.000 anggota komunitas keagamaan Gafatar dari rumah dan lahan pertanian mereka di Pulau Kalimantan sejak Januari 2016, menurut Human Rights Watch hari ini.
Riset Human Rights Watch di Kalimantan Barat dan Timur menemukan fakta bahwa aparat keamanan gagal melindungi anggota Gerakan Fajar Nusantara, biasa disingkat Gafatar. Mereka diam saja saat pemuda etnik Melayu dan Dayak mengancam, mengusir, menjarah serta menghancurkan barang-barang milik Gafatar. Pemerintah lantas memindahkan para anggota Gafatar ke tempat penahanan tak resmi, kemudian mengirim ke kampung halaman masing-masing, bukan sebagai sebuah perlindungan, melainkan sebagai upaya membubarkan keberadaan Gafatar, menurut Human Rights Watch.
“Beberapa gerombolan etnik dan lembaga pemerintah bertindak atas nama ‘kerukunan beragama’ mengabaikan hak asasi berupa keamanan dan kebebasan beragama anggota Gafatar,” kata Phelim Kine, wakil direktur Asia dari Human Rights Watch. “Lembaga pemerintah dan aparat keamanan tak berbuat banyak untuk memberikan perlindungan kepada anggota Gafatar dari penggusuran, pengurungan, dan mengirimkan mereka ke daerah-daerah asalnya.”
Polisi dan militer memang mencegah terjadinya kekerasan fisik pada anggota Gafatar, namun hanya mengevakuasi dari Kalimantan ke Jawa, kata puluhan anggota Gafatar pada Human Rights Watch. Pemerintah sewenang-wenang menahan, menginterogasi, dan mengancam mereka seperti layaknya kriminal.
Penggusuran dan penahanan menyusul gelombang kebencian kepada anggota Gafatar, dimulai oleh laporan berbagai media sejak awal Januari, yang menuduh komunitas ini terlibat penculikan dan perekrutan paksa. Anggota Gafatar telah lama dicurigai landasan sistem kepercayaannya karena menggabungkan Islam dengan kepercayaan Kristen dan Yahudi, dengan tuduhan “ajaran sesat dan menyesatkan.”
Laporan beberapa media juga menuduh bahwa Gafatar memiliki kecenderungan untuk bikin gerakan separatis, tanpa bukti kuat, dan menciptakan negara agama (teokrasi) di Kalimantan. Mereka dituduh dengan label “Negeri Karunia Tuan Semesta Alam.”
Pada 14 Januari, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengintruksikan pemerintah daerah untuk menutup semua kantor Gafatar. Pada 24 Maret, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB), yang diteken bersama Menteri Agama Lukman Saifuddin dan Menteri Dalam Negeri Kumolo, yang memperingatkan “mantan anggota dan pengurus Gafatar” untuk terlibat “… penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam.” Hukuman atas pelanggaran tersebut maksimal penjara lima tahun, berdasarkan pasal pidana penodaan agama keluaran 1965.
Dalam pertemuan pers 24 Maret, Jaksa Agung Prasetyo, “Kami meminta masukan kepada semua pihak dari unsur Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dari TNI dan Kejaksaan sendiri. Terakhir MUI telah mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwa ajaran Gafatar itu dinilai sesat dan menyesatkan kalau itu didiamkan bisa menimbulkan keresahan dan berbagai SARA.”
Juru bicara Gafatar Farah Meifira mengatakan pada Human Rights Watch bahwa 2.422 keluarga, total 7.916 individu termasuk anak-anak, diusir dari Kalimantan Barat dan Timur sejak Januari sampai akhir Februari. Pemerintah Indonesia menahan lebih dari 6.000 anggota Gafatar yang diusir paksa dari Kalimantan ke enam tempat penahanan tak resmi di Jakarta, Yogyakarta, Bekasi, Boyolali dan Surabaya. Human Rights Watch tak dapat memverifikasi secara independen keseluruhan informasi tersebut namun kami mengunjungi tiga tempat penahanan di Jawa, dalam dua minggu pertama Februari, ada sekira 800 anggota Gafatar masing-masing di sana. Pada akhir Maret, ada lebih dari 300 anggota Gafatar, termasuk di antaranya 100 anak-anak, masih berada di penahanan Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Ada 302 orang dikirimkan ke kampung halaman mereka di Sumatera Utara pada 30 Maret 2016.
Anggota Gafatar mengatakan para petugas melarang mereka meninggalkan tempat penahanan kecuali untuk keperluan singkat seperti membeli makanan dan keperluan lain. Mereka berkata bahwa pemerintah memberi mereka, “pembinaan agama,” ”penyuluhan deradikalisasi,” dan ancaman pidana penodaan agama. Di dalam pengungsian di Boyolali, Jawa Tengah, aparat militer mendoktrin sekira 1.000 anggota Gafatar tentang pendidikan “bela negara,” sebuah sesi masing-masing sehari untuk bahas Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan.
Sejak pertengahan Februari, pemerintah memang telah melepaskan sebagian besar anggota Gafatar, tapi gagal menjalankan amanat undang-undang dalam melindungi hak beragama, hak bergerak, dan hak mereka berkumpul. Anggota Gafatar berkata bahwa pemerintah Indonesia tak membantu dalam pengembalian aset dan keamanan mereka untuk kembali ke Kalimantan.
Alih-alih mengembalikan anggota Gafatar ke Kalimantan, pemerintah justru menekan mereka ke daerah asal masing-masing. Pemerintah membuat aturan mengenai relokasi paksa dan menyerahkan anggota Gafatar kepada pemerintah daerah atau kerabat mereka.
Pemerintah Indonesia seharusnya hentikan kriminalisasi komunitas Gafatar, ujar Human Rights Watch. SKB anti-Gafatar, yang melarang Gafatar, seyogyanya dibatalkan. Pemerintah juga seharusnya membantu anggota Gafatar untuk kembali ke rumah dan lahan pertanian mereka di Kalimantan, dan menyediakan keamanan yang efektif untuk melindungi mereka dari berbagai gangguan dan kekerasan. Ini juga terkait dengan disediakannya kompensasi yang tepat dan memadai guna mengganti berbagai aset mereka yang hilang. Lembaga penegakan hukum juga seharusnya menyelidiki dan mengusut pejabat pemerintah pusat, anggota aparat keamanan, dan pemerintah daerah, yang terlibat dalam pengusiran serta berbagai kegiatan melawan hukum terhadap anggota Gafatar.
“Pengabaian hak asasi anggota Gafatar merupakan satu lagi keterlibatan pemerintah Indonesia dalam mendorong tumbuhnya intoleransi atas nama agama di Indonesia," ujar Kine. "Anggota Gafatar, seperti halnya kaum Syiah, Ahmadiyah dan beberapa gereja Kristen, sudah belajar dari pengalaman pahit mereka bahwa pemerintah dan aparat keamanan, yang seharusnya melindungi semua warga Indonesia, termasuk minoritas agama, justru menunjukkan penolakan terhadap kebebasan beragama."
Kriminalisasi kepada Komunitas Keagamaan Gafatar
Human Rights Watch mewawancarai 34 anggota Gafatar, termasuk enam perempuan dan satu anak, di Jakarta, Bekasi, dan Yogyakarta antara 1 Februari sampai dengan 23 Maret 2016. Wawancara berlangsung di luar tempat penahanan tak resmi milik pemerintah bagi ribuan anggota Gafatar di tiga kota tersebut setelah pengusiran dari Kalimantan.
Dalam wawancara Human Rights Watch, para anggota Gafatar mengatakan akses orang luar, termasuk aktivis hak asasi manusia dan wartawan, ke tempat penahanan tak resmi diawasi dengan ketat. Human Rights Watch juga mewawancarai pejabat pemerintah dan aparat keamanan di Jakarta dan Pontianak, seorang pengurus Majelis Ulama Indonesia di Pontianak, dan beberapa tokoh Dayak di Kalimantan Barat.
Gafatar dan Intoleransi pada Minoritas Beragama
Gafatar adalah sebuah organisasi, sekaligus sebuah sekte Islam, yang dideklarasikan pada Januari 2012 dan berkantor pusat di Jakarta. Menurut Farah Meifira, juru bicara Gafatar, mereka memiliki lebih dari 55.000 anggota dan memiliki cabang di 34 provinsi di Indonesia. Guru spiritual Gafatar, Ahmad Mushaddeq, adalah seorang Muslim sufi dan mendirikan kelompok Al Qiyadah Al Islamiyah dengan tafsir sendiri soal Islam. Ia dipenjara selama empat tahun dengan tuduhan penodaan Islam pada 2008.
Keyakinan kelompok tersebut membuat mereka dituduh melakukan “penyimpangan agama” berdasarkan pasal penodaan agama tahun 1965, yang hanya melindungi enam keyakinan – Islam, Katolik, Protestan, Konghucu, Budha, dan Hindu. Dua anggota Al Qiyadah Al Islamiyah juga dipenjara di Padang, Sumatera Barat, pada 2008. Pada 2015, enam anggota Gafatar dihukum tiga sampai empat tahun penjara di Banda Aceh. Kementerian Dalam Negeri menolak memperpanjang izin organisasi masyarakat Gafatar dengan alasan doktrin pada 2015 sehingga membuat para pengurus Gafatar membubarkan diri dan menyebut diri mereka “ex-Gafatar.”
Kini komunitas Gafatar adalah target terbaru dari makin buruknya intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang menyerang minoritas agama di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir. Di seluruh Indonesia, minoritas beragama termasuk Muslim Syiah, beberapa gereja Kristen, dan Ahmadiyah, adalah target dari pelecehan, intimidasi, ancaman, dan kekerasan. Setara Institute, yang memantau kebebasan beragama di Indonesia, mendokumentasikan berbagai kasus kekerasan yang menyerang minoritas beragama dalam satu dasawarsa, termasuk 214 kasus di tahun 2014 dan 197 kasus pada 2015.
Organisasi Islam intoleran, termasuk Front Pembela Islam, biasa memobilisasi massa “pendemo” untuk mengganggu dan mengintimidasi minoritas serta rumah ibadah mereka. Para pemimpinnya menyatakan bahwa mereka membela Islam untuk melawan “orang kafir” dan “orang yang menghina Islam.” Mereka sering mengganggu prosesi ibadah minoritas agama dengan pengeras suara serta membuang bangkai binatang dan kotoran di depan pintu rumah ibadah.
Lembaga semi-pemerintah Majelis Ulama Indonesia, yang menyarankan pemerintah untuk membuat aturan soal agama, ikut bikin diskriminasi dengan berbagai fatwa yang menyudutkan minoritas agama. MUI membuat fatwa di tahun 2005 yang menyatakan bahwa Ahmadiyah menyimpang dari Islam, dan Februari lalu membuat fatwa untuk menyerang Gafatar dengan tuduhan penyimpangan Islam. Organisasi Islam moderat, termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sedikit bicara soal penyerangan terhadap minoritas beragama atau secara terbuka menentang fatwa MUI. Beberapa pemimpin mereka ikut tandatangan berbagai fatwa MUI yang menyudutkan minoritas.
Institusi negara secara langsung juga melanggar hak dan kebebasan beragama minoritas. Human Rights Watch menyimpulkan bahwa Kementerian Agama dan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) di bawah Kejaksaan Agung, telah mengikis kebebasan beragama dengan menggunakan fatwa guna menyudutkan agama-agama minoritas dan menekankan kriminalisasi kepada “penodaan” agama. Semua institusi tersebut ikut kontribusi dalam kampanye anti-Gafatar.
Penyerangan Terencana terhadap Komunitas Gafatar
Anggota Gafatar mengatakan pada Human Rights Watch bahwa sejak 15 Januari 2016, gerombolan dengan pentungan dan golok di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, mendatangi kelompok tani Gafatar dan minta Gafatar meninggalkan Mempawah dalam tiga hari. Anggota Gafatar berkata bahwa pejabat pemerintah dan pihak kepolisian juga mengunjungi pertanian mereka dan menekan mereka mengabulkan tuntutan tersebut. Pihak keamanan secara terbuka menyebut pembunuhan massal etnik Madura pada 1990an di Sambas dan Sampit. Mereka menakut-nakuti anggota Gafatar bahwa mereka bisa jadi korban pembunuhan etnik Madura macam di Sambas pada 1999, dekat Mempawah. Pembunuhan massal tersebut terjadi antara lain karena sentimen etnik Dayak versus Melayu ditambah oleh kegiatan pemerintah di bidang transmigrasi sejak 1970an dengan mengirim puluhan ribu keluarga miskin dari Pulau Jawa ke daerah yang kurang padat penduduk di Indonesia termasuk Kalimantan.
Pada 18 Januari, ratusan orang Melayu, sebagian dengan ikat kepala warna kuning, menyerang dua kelompok tani Gafatar, di desa Kampung Pasir dan Antibar di Mempawah. Sebuah video amatir dari Antibar memperlihatkan polisi dan tentara diam saja ketika massa Melayu merusak barang-barang dan membakar delapan rumah panjang. Berikutnya militer dan polisi evakuasi sekitar 1600 anggota Gafatar dengan truk ke markas Pembekalan dan Angkutan Kodam Tanjungpura (Bekangdam) di Pontianak. Angka mereka semakin bertambah ketika terjadi pengusiran paksa Gafatar dari kabupaten lain termasuk Kubu Raya, Melawi, Landak, dan Bengkayang. Aksi menolak Gafatar dalam beberapa hari melebar ke seluruh Kalimantan Barat dan Timur.
Banyak anggota Gafatar menggambarkan bahwa polisi dan tentara terlibat dalam pengusiran tersebut. Mereka bilang, saat insiden terjadi, polisi dan militer hanya berdiri saat massa mulai menyerang rumah dan menjarah barang-barang, turun tangan hanya untuk mencegah luka fisik kepada anggota Gafatar dan mengevakuasi mereka. Dalam tiga minggu, pemerintah Kalimantan Barat dan Timur mengirimkan lewat jalur udara dan laut, memindahkan ribuan anggota Gafatar ke berbagai pusat penahanan tak resmi di Jawa. Pada 3 Februari 2016, Majelis Ulama Indonesia mengumumkan fatwa Gafatar sebagai organisasi “sesat.” Menteri Koordinator Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendukung kriminalisasi terhadap anggota Gafatar karena “penodaan agama dan perbuatan makar.”
Standar Hukum yang Relevan
Pemerintah Indonesia melalui konstitusi dan perjanjian internasional membuat komitmen untuk menghormati hak kebebasan beragama. Ia bahkan telah menjadi bagian dari Undang-undang Dasar 1945 ketika Republik Indonesia menyatakan kemerdekaan pada Agustus 1945. Pada tahun 2005 Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, termasuk pasal 18(2) yang menyebut, “Tidak ada seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya,” dan di dalam pasal 27 bahwa “orang-orang yang tergolong dalam … kelompok minoritas tidak boleh diingkari haknya, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri atau menggunakan bahasa mereka sendiri.”
Komite Hak Asasi Manusia PBB, badan ahli internasional yang mengawasi kepatuhan negara terhadap Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, menegaskan dalam komentar umumnya nomor 22 bahwa lembaga itu “melihat dengan seksama setiap tendensi untuk mendiskriminasi terhadap agama apapun atau kepercayaan untuk alasan apapun, termasuk kenyataan bahwa mereka… mewakili minoritas keagamaan yang mungkin menjadi subyek kekerasan oleh sebagian komunitas keagamaan dominan.” Pada Februari 2013, pelapor khusus PBB untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan, Heiner Bielefeld, memperingatkan bahwa ada bagian-bagian dari Rancangan Undang-undang Organisasi Masyarakat “yang bisa mengganggu kebebasan beragama atau berkeyakinan.” Bielefeld, bersama pelapor khusus untuk kebebasan berasosiasi dan berekspresi, mendorong pemerintah untuk merevisi rancangan tersebut agar “sejalan dengan norma dan standar HAM internasional.”
Hukum internasional juga melindungi setiap orang dari penggusuran. Istilah “penggusuran paksa” didefinisikan oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB sebagai pemindahan sementara maupun permanen di luar kehendak individu, keluarga, dan/atau komunitas dari rumah dan/atau tanah yang mereka tempati, tanpa ketentuan dari, dan akses kepada, hukum dan bentuk perlindungan yang semestinya.
UUD 1945 pasal 28 (H) ayat 1 menjamin, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menegaskan jika “setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.”
Komite Ekonomi, Sosial dan Hak Budaya menyimpulkan jika “penggusuran jelas bertentangan” dengan tuntutan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Sebagai tambahan, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik melindungi hak individu dari “intervensi sewenang-wenang dan melanggar hukum atas privasinya, keluarga, rumah atau korespondensi,” dan menjamin setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum melawan intervensi atau serangan semacam itu.
Penggusuran juga bisa berujung pada pelanggaran terhadap hak-hak yang dilindungi dengan baik oleh hukum Indonesia maupun internasional. Penggusuran melanggar hak untuk bebas bergerak dan bebas memilih tempat tinggal. Pelanggaran dan penghancuran serampangan mengancam hak atas jaminan keselamatan seseorang. Gangguan terhadap proses belajar-mengajar anak-anak bisa menyebabkan pelanggaran terhadap hak atas pendidikan.
Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Pemindahan Internal (selanjutnya disebut Prinsip Panduan) berlaku untuk orang yang dipaksa meninggalkan rumah mereka, termasuk saat terjadi kekerasan luas atau pelanggaran hak asasi manusia (Pembukaan). Prinsip Panduan melindungi setiap orang dari pemindahan rumah mereka karena praktek yang bermaksud mengubah komposisi agama dari populasi penduduk (prinsip 6). Pemerintah seharusnya melindungi mereka yang dipindah dari penangkapan diskriminatif dan penahanan sebagai akibat pemindahan mereka (prinsip 12). Harus dipastikan yang dipindahkan memiliki hak untuk bebas bergerak dan hak untuk memilih tempat tinggal mereka sendiri (prinsip 14).
Otoritas yang kompeten memiliki kewajiban utama dan tanggungjawab untuk membangun kondisi yang akan mengizinkan orang-orang yang terusir ini untuk “kembali dengan sukarela, dalam kondisi aman dan bermartabat” ke rumah mereka, atau membangun lagi secara suka rela di daerah lain dalam negeri (prinsip 28). Mereka juga bertanggung jawab untuk mendampingi mereka yang kembali atau membangun kembali untuk memulihkan properti dan harta mereka, atau memperoleh kompensasi yang sesuai atau bentuk lain dari ganti rugi yang layak (pasal 29).
Para Anggota Gafatar Menggambarkan Intimidasi, Kekerasan, dan Penggusuran
Penggusuran dari Kalimantan
Dwi Adiyanto, pengusaha usia 30 tahun asal Yogyakarta, menuturkan:
Kami survei tiga daerah di Kalimantan Barat pada Juni 2015: Pontianak, Bengkayang, dan Mempawah. Anggota kami di Yogyakarta setuju untuk pindah ke Mempawah. Kami membeli dan menyewa lahan sebanyak 16 hektar di desa Kampung Pasir, Mempawah. Kami melakukannya secara sah dan sesuai hukum adat, membangun 10 rumah panjang. Kami mulai membangun lahan pertanian pada Agustus 2015. Total, ada 329 anggota kami dari Yogyakarta.
Pada 14 Januari 2016, di tengah memuncaknya histeria media [dugaan penculikan yang dilakukan Gafatar pada seorang dokter, Rica Handayani], beberapa pejabat pemerintah, polisi dan tentara mendatangi lahan kami bersama sekitar 50 orang Melayu. Mereka mengajukan banyak pertanyaan tentang pertanian dan keyakinan kami. Seorang mantan kepala desa lantas kasih ultimatum. Dia minta kami meninggalkan Mempawah dalam waktu 3x24 jam. Dia menakut-nakuti dengan pembantaian Sambas dan Sampit. Pukul 22:30 pertemuan selesai, tapi mereka memerintahkan kami semua —total sebanyak 28 laki-laki, perempuan dan anak-anak—untuk berbaris di depan mereka. Itu tekanan psikologis, khususnya bagi anak-anak kami.
Pada 15 Januari, kami hadir dalam rapat di Kantor Bupati Mempawah yang dipimpin oleh Wakil Bupati Gusti Ramlana beserta kepala kepolisian, komandan militer, kejaksaan, Majelis Ulama Indonesia, dan para kepala desa. Kami bersembilan: lima laki-laki Gafatar dari Kampung Pasir yang datang dari Yogyakarta, dan empat dari desa Antibar yang berasal dari Jawa Timur. Gusti Ramlana terus menekan kami untuk “mengikuti kemauan masyarakat … kembali ke Jawa.” Kapolres Mempawah Suharjimantoro minta pertemuan ditunda untuk menunggu keputusan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis pada Gafatar. Belakangan kami paham jika Cornelis ingin anggota Gafatar meninggalkan Kalimantan.
Pada 18 Januari, kami menghadiri pertemuan lanjutan di Kantor Bupati Mempawah yang diketuai oleh Bupati Ria Norsan. Itu pertemuan menegangkan, ratusan pendemo di luar gedung. Hingga sore, kami minta dasar hukum pengusiran kami. Mereka hanya pakai alasan tekanan massa. Kami tetap menolak dan penolakan tersebut dibocorkan keluar, bahkan diberitakan media Pontianak, bisa dibaca lewat internet. Massa membakar Toyota Avanza putih milik kami. Ini memberi tekanan agar kami setuju pergi.
Ironisnya, polisi memutuskan untuk mengamankan kami, total 10 orang, minta kami naik ke truk polisi. Kami dibawa ke markas Brimob Pontianak. Kami ditahan, diperiksa dan dituduh penodaan agama. Kami tak diberi izin menunjuk pengacara. Keluarga dilarang datang. Kami ditahan seminggu ketika keluarga kami semua dievakuasi dari Mempawah ke Bekangdam Pontianak.
Pada 25 Januari, kami dipindahkan ke tahanan Polda Kalimantan Barat. Kami kembali diinterogasi untuk informasi tambahan atas dugaan penodaan agama. Hari itu juga kami diterbangkan ke Surabaya dan ditahan di tempat pengungsian milik pemerintah selama seminggu, bersama ratusan anggota Gafatar lain. Saya dipindahkan ke Yogyakarta dimana saya ditahan lagi di penampungan pemerintah sampai saya dibebaskan 2 Februari.
Edhi Hartomo (nama samaran), pengusaha, usia 42 tahun asal desa Limau Manis, kecamatan Pulau Maya, Kalimantan Barat:
Saya lahir di Pulau Maya. Ayah saya juga lahir di Pulau Maya tapi ibu saya dari Pontianak. Saya bantu mendirikan empat kelompok Gafatar di Pulau Maya, masing-masing dari Riau, Bangka-Belitung, Aceh dan Jambi. Total 33 hektar lahan pertanian.
Pada 23 Januari 2016, polisi, tentara, dan pejabat pemerintah datang ke Limau Manis. Mereka menjemput dan menahan saya, istri, dan empat anak saya. Dalihnya, melindungi kami dari kemungkinan kekerasan.
Pada 24 Januari, ketika saya sudah ditahan, mereka datang kembali [ke Pulau Maya] bersama banyak preman, minta anggota Gafatar meninggalkan Pulau Maya dalam 2x24 jam. Mereka mengatakan kami akan dikembalikan ke kampung halaman di Jawa. Saya bilang kampung halaman adalah Pulau Maya. Saya memiliki banyak kerabat di Pulau Maya maupun Pontianak. Mau pulang kemana?
Saya tidak mau dibawa ke Jawa. Militer menolak argumentasi saya. Mereka bawa kami semua ke kapal TNI Angkatan Laut ke Jakarta. Itu kapal militer. Kami seperti sarden. Anak-anak banyak yang sakit selama perjalanan semalam. Kami tiba di Jakarta pada 1 Februari dan ditahan di asrama haji milik Kementerian Agama di Bekasi.
Agustiar, instruktur pertanian asal Kuningan, Jawa Barat:
Pada 15 Januari, istri saya membangunkan saya. Dia bilang ada protes melawan kita dekat lahan pertanian. Sekitar 300 orang mengepung sawah kami dan menuntut pergi. Polisi, tentara, dan pejawab pemerintah segera datang, menekan kami untuk pergi dalam 2x24 jam. Kami tidak setuju [ditekan seperti itu], tapi menyadari bahayanya. Kami minta [polisi] memberi kami waktu. Bagaimana bisa kami meninggalkan sawah kami, berton-ton benih, traktor, dan peralatan lain hanya dalam dua hari?
Dua hari kemudian situasi tegang, ada demonstrasi ratusan preman di luar pertanian kami dan teriak mengusir kami. [Gafatar] perempuan dan anak-anak bersembunyi di dekat hutan. Hanya lelaki Gafatar menjaga rumah.
Pada 19 Januari, lebih dari seribu preman, dengan ikat kepala kuning, menyerang sawah kami, membakar rumah-rumah dan merusak tanaman padi. Polisi dan militer tidak berusaha menghentikan. Mereka hanya melarang para preman melakukan kekerasan pada kami. Militer membawa kami ke dalam truk lantas menuju Bekangdam di Pontianak. Kami tinggal di sana sampai 25 Januari lantas dibawa dengan kapal TNI Angkatan Laut ke Jakarta.
Andry Cahya, pengusaha agrobisnis berusia 48 tahun dan anak tertua dari guru spiritual Gafatar Ahmad Mushaddeq:
Secara total, kami memiliki lahan 125 hektar di Kabupaten Melawi. Ini kepemilikan bersama, dimiliki atau disewa oleh 21 keluarga Gafatar termasuk saya. Kami tanam kebanyakan jahe buat ekspor ke Belanda. Harganya sangat bagus. Ekspor pertama 225 ton jahe dan dapat tiga juta Euro (Rp 45 milyar). Gafatar ingin ikut bangun ketahanan pangan di Indonesia. Mengapa dilarang?
Ketika kekerasan pecah, saya berada di Pontianak. Kami masih ada 15 ton bibit jahe dan 4 ton kunyit di Melawi. Semuanya musnah. Secara pribadi saya kehilangan dua sapi. Saya jual 12 sapi lainnya dengan harga murah.
Pemerintah Kalimantan Barat mengerahkan tiga kapal TNI Angkatan Laut, satu kapal komersial, dan sembilan pesawat Lion Air untuk evakuasi kami dari Kalimantan Barat. Saya tidak tahu kerugian non-material yang kami derita. Kami ingin kembali ke tanah kami dan bekerja di sana.
Herman (nama samaran), koordinator Gafatar usia 29 tahun di desa Sukamaju, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat:
Pada 11 Januari, saya dipanggil ikut rapat di balai desa. Kami menunjukkan semua dokumen tanah, surat kependudukan dan lainnya. Kami diminta menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa kami tidak memiliki niat buruk terhadap masyarakat dan negara. Kami tandatangani. Kami juga sampaikan data 345 anggota kami di Ketapang berasal dari Jawa Tengah dan Sumatra Utara.
Pada 19 Januari, perintah pengusiran keluar. Deadline 24 Januari. Kami tidak boleh menawar. Pejabat desa mengatakan perintah datang dari Jakarta dan Pontianak. Persis 24 Januari, ada banjir. Badan SAR Nasional menggunakan perahu karet untuk membawa kami ke jalan utama, lalu dipindah truk untuk dibawa ke [kota] Ketapang. Jalanan rusak. Seorang perempuan hamil segera dilarikan ke rumah sakit di Ketapang. Kami ditaruh di bekas gudang semen di Ketapang.
Pada 26 Januari, kami mesti berlayar ke Semarang [Jawa Tengah] dengan kapal yang kelebihan beban. Kapasitas 600 orang, kapal itu membawa 1.300 anggota Gafatar. Di Semarang, kami dibawa ke Boyolali dan ditahan lagi sampai pemerintah daerah membawa kami masing-masing. Kami diberi kuliah soal bela negara termasuk Pancasila. Kami ingin mendapatkan ganti rugi atas harta kami [yang hilang dan dirusak] di Ketapang.
Pembatasan, Pelanggaran di Tempat Penahanan Tak Resmi
Saat kekerasan terhadap komunitas Gafatar memuncak, pejabat pemerintah daerah –terutama dari kantor Kesatuan Bangsa dan Politik-- maupun polisi, tentara, serta pejabat dari Kementerian Sosial dan Kementerian Agama menahan lebih dari 6.000 anggota Gafatar. Mereka diusir paksa dari Kalimantan, ditempatkan setidaknya di enam tempat penahanan tak resmi di Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Tempat penahanan tersebut meliputi barak militer dan asrama haji, dan tempat yang tidak didesain untuk menampung banyak orang, katakanlah, gudang pabrik semen, gelanggang olahraga, dan balai kepemudaan, dengan penjagaan polisi, tentara, pejabat daerah maupun pegawai Kementerian Sosial dan Kementerian Agama.
Susi (nama samaran), ibu rumah tangga 30 tahun yang hamil 5 bulan ketika massa mengusir paksa keluarganya dari rumah mereka di desa Lempai Jaya, Kalimantan Barat, mengatakan:
Pada 22 Januari, suami saya menerima 32 pejabat pemerintah daerah, polisi dan tentara, yang minta kami meninggalkan lahan pertanian kami dalam 24 jam. Mereka mengatakan massa akan serang kami.
Saya sedang hamil. Saya juga mengasuh dua anak saya. Kami tidak memiliki pilihan lagi kecuali pergi. Kami dievakuasi dengan beberapa bus dan truk ke Kantor Bupati Melawi dan kemudian di Bekangdam di Pontianak. Di sana sudah ada dua kelompok tani Gafatar [juga diusir dari] Melawi.
Tidak ada dokter yang memeriksa kehamilan saya, Melawi maupun Pontianak. Kami biasa makan makanan organik dari sawah kami, tapi di pusat pengungsian, kami [hanya] diberi Indomie dan sarden kaleng mentah. [jadi] Malnutrisi adalah masalah kami. Kami menghabiskan banyak uang selama perjalanan untuk makanan tambahan anak-anak.
Adi (nama samaran) tinggal di sebuah lahan pertanian Gafatar, desa Suka Maju, Kalimantan Barat saat peristiwa pengusiran terjadi:
Saya diusir 26 Januari, tinggal semalam di gudang semen di Ketapang dan kemudian dibawa kapal TNI Angkatan Laut menuju Semarang [Jawa Tengah]. Pakai 13 bus untuk bawa 302 anggota Gafatar ke asrama haji di Boyolali. Ada lebih dari 1.600 orang di asrama tersebut.
Kami wajib mengikuti pembinaan bela negara, pelajaran agama selama tiga hari, termasuk pasal penodaan agama. Mereka juga menugaskan seorang psikiater untuk mengajari kami, mencoba membuat kami percaya bahwa kami menderita sakit mental. Kami tidak diizinkan keluar asrama. Gedung tersebut dijaga polisi, tentara beserta pejabat dari beberapa kementerian.
Setelah dua minggu, kebanyakan anggota Gafatar dipindahkan ke provinsi tempat mereka berasal tapi tidak termasuk kami, 302 orang dari Sumatera Utara. Kami tinggal di sana hampir dua bulan. Pemerintah Sumatera Utara bilang mereka belum memiliki dana untuk menjemput kami.
Hadi Suparyono, koordinator Gafatar asal Yogyakarta di Mempawah, Kalimantan Barat, yang sedang diperiksa di Jakarta atas tuduhan penodaan agama dan makar terhadap negara.
Di Yogyakarta, [saya] ditahan di Youth Center dengan total 248 anggota Gafatar. Istri saya menelepon dan mengatakan bahwa anak kami sedang dirawat di rumah sakit Muhammadiyah [Yogyakarta]. Sejak ditahan di Brimob Pontianak, saya dilarang bertemu keluarga dan pengacara.
Sekarang anak saya sakit, saya minta izin tengok anak. Pegawai pemerintah yang menjaga gedung [Youth Center] tidak mengizinkan saya pergi. Mereka mengatakan bahwa mereka diperintahkan untuk menjaga kami tetap di dalam gedung. [Pembatasan yang sama] terjadi di Pontianak, Surabaya, dan sekarang Yogyakarta. Hanya setelah meminta pada perwira berpangkat lebih tinggi saya diizinkan menjenguk anak saya, [tetapi] hanya 45 menit di rumah sakit. Saya didampingi beberapa petugas untuk mengunjungi rumah sakit.
Andi (nama samaran), anggota Gafatar di Singkawang, Kalimantan Barat, menjelaskan suasana penampungan Gelanggang Olahraga POPKI di Cibubur, Jakarta, sesudah evakuasi 1 Februari 2016:
Keluarga saya tinggal di Depok. Saya berusaha menghubungi keluarga untuk bertemu, tapi saya punya keterbatasan pulsa. Ditambah, oleh keluarganya, istri saya tak boleh bertemu dengan saya. RT, RW, maupun Kelurahan mendatangi rumah keluarga saya di Depok untuk memberitahu bahwa saya ikut aliran sesat. Keluarga besar saya percaya. Mereka marah.
Saya tidak bisa keluar. Kami semua harus tinggal di dalam sampai pemerintah Depok menjemput kami. Jika penjemputan itu dilakukan secara tertutup masih tak masalah, tapi petugas bilang kami akan diantar pulang dengan iring-iringan sebagai efek jera. Saya sangat malu jika itu benar-benar terjadi.
Ada petugas keamanan yang menjaga stadion. Makanan yang disediakan hanya Indomie dan nasi. Anak-anaklah yang paling menderita, batuk, depresi, dan trauma. Kami coba beli susu dan makanan tambahan dari para penjual tapi kami tidak bisa keluar. Akhirnya ada beberapa penjaja makanan bersedia mengirim makanan lewat pagar [stadion].
Anton (nama samaran), koordinator Gafatar berusia 35 tahun di Ella Hilir, Kabupaten Meawi, Kalimantan Barat, yang keluarganya diusir pada 23 Januari:
Kami dievakuasi oleh KRI Teluk Penyu dari Pontianak. Susah sekali perjalanan selama dua hari dalam kapal perang. Tidak ada kamar. Kami ditempatkan di perut kapal, tidur di lantai, penuh sesak. Di pelabuhan Tanjung Priok [Jakarta], kami diangkut dengan bus dan truk menuju asrama haji di Bekasi.
Di sini ada kamar dan kasur. Tapi juga penuh. Keluarga bisa bertemu kami dalam gedung tapi harus minta izin [Kementerian Agama]. Saya memiliki tiga puteri. Dua jatuh sakit. Mereka kelelahan dan stress. Kami harus antri untuk menggunakan kamar mandi.
Pembatasan Tanpa Henti Hak-Hak Anggota Gafatar
Sejak pertengahan Februari, pemerintah Indonesia mulai melepaskan kebanyakan anggota Gafatar yang ditahan, tapi gagal melindungi hak-hak mereka untuk bergerak secara bebas, beragama, dan berkumpul. Para anggota Gafatar menyaksikan pemerintah gagal mengkritisi pernyataan Dewan Adat Dayak, yang melarang Gafatar kembali ke Kalimantan, sebagai keterlibatan pasif dalam pengusiran paksa mereka.
Anggota Gafatar berpendapat langkah pemerintah pusat mengembalikan mereka ke daerah masing-masing, menyusul dibebaskannya mereka dari tempat penahanan, secara efektif mendukung pengusiran dari Kalimantan. Usaha pemerintah untuk menghalangi Gafatar kembali ke Kalimantan termasuk rencana pemerintah daerah Jakarta menawarkan perumahan murah dengan syarat anggota Gafatar tidak tinggal bersama untuk menghindari “masalah.” Para anggota Gafatar mengatakan bahwa pemerintah juga gagal memenuhi komitmen untuk memberi kompensasi bagi para anggota Gafatar yang diperkirakan kehilangan aset senilai Rp 30,4 miliar.
Pejabat pemerintah di Pontianak, Kalimantan Barat, menyebut pengusiran paksa Gafatar dari Kalimantan sebagai “evakuasi” untuk melindungi keamanan komunitas Gafatar. Para anggota Gafatar mengatakan bahwa pejabat pemerintah dan aparat keamanan membenarkan peranan tersebut guna mencegah kekerasan massa terulang dalam pembunuhan massal terhadap etnik Madura di Sambas, Kalimantan Barat, dan Sampit, Kalimantan Tengah, antara 1999 dan 2001.
Pejabat pemerintah kemudian menggambarkan penahanan anggota Gafatar sebagai bagian dari “proses registrasi.” Para anggota Gafatar mengatakan bahwa proses tersebut termasuk foto wajah (mugshots) dan pengambilan sidik jari—termasuk ratusan anak-anak-- yang menurut pejabat pemerintah penting guna “pemantauan masa depan ”. Meski pemerintah menyediakan konseling untuk trauma anak-anak Gafatar di tempat penampungan, pembatasan gerak terhadap mereka membuat mereka mustahil mendatangi sekolah selama periode penahanan tak resmi. Polisi menanyai setidaknya 19 anggota Gafatar, termasuk ketua organisasi tersebut, tentang kemungkinan pelanggaran hukum penodaan agama di Indonesia.
Prasetya (nama samaran), anggota Gafatar desa Suka Maju, Kalimantan Barat, berusia 34 tahun:
Di Boyolali [asrama haji], petugas memeriksa KTP dan menemukan bahwa saya terdaftar sebagai warga Solo. Tapi Solo sebenarnya bekas tempat tinggal saya. Rumah sewaan saya sesungguhnya ada di Kabupaten Karanganyar, dekat Solo.
Saya tidak ganti KTP ketika saya pindah ke Kalimantan. Masalahnya, kedua pemerintah daerah [Karanganyar dan Surakarta] menolak menerima saya. [Jadi] tinggal lebih lama di Boyolali. Mereka mengatakan saya bisa meninggalkan tempat penampungan jika ada tetangga saya [di Surakarta] bisa menjemput saya. Ini sulit [mengaturnya] saat bersamaan dengan segala pemberitaan media yang menyebut Gafatar sebagai sesat. Saya juga kuatir sulit menemukan pekerjaan dengan semua stigma kepada Gafatar.
Dewi (nama samaran), ibu rumah tangga berusia 29 tahun di Cilacap, yang menikah dengan anggota Gafatar tapi tidak terlibat dalam kelompok tani di Kalimantan:
Ketika suami saya, ditahan di Pontianak pada Januari, dia protes soal perlakuan yang mereka terima di Bekangdam. Tampaknya itu berdampak pada saya. [Tidak lama setelah dia membuat pernyataan,] polisi Cilacap mendatangi rumah saya, menyita laptop saya, telepon saya, lusinan buku, dan beberapa USB. Saya diinterogasi dan ditetapkan sebagai “saksi dari penodaan agama.” Tetapi polisi tidak memberitahu saya siapa tersangkanya. Itu bikin sedikit masalah di lingkungan tempat tinggal saya. Saya diperlakukan berbeda [oleh tetangga-tetangga saya] sejak polisi menggerebek rumah kami.
Eka (nama samaran), insinyur teknik sipil perempuan yang tinggal di Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dan dievakuasi paksa ke Jakarta, pada Februari 2016:
Dua perempuan Gafatar melahirkan ketika ditahan di Bekangdam Pontianak. Mereka melahirkan di rumah sakit tapi harus kembali ke barak militer. Air minum berasal dari Sungai Kapuas [yang berpolusi] dekat Bekangdam. Sidik jari saya diambil. Wajah saya juga dipotret seperti kriminal. Saya memiliki catatan dalam database kepolisian. Bagaimana caranya kelak bisa mendapatkan pekerjaan? Buat saya Gafatar sudah selesai. Saya mau melupakannya.
Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.
Topic
Most Viewed
-
March 18, 2021
“Aku Ingin Lari Jauh”

-
October 17, 2023
Israel: Fosfor Putih Digunakan di Gaza dan Lebanon

-
October 23, 2023
Israel/Palestina: Video Serangan Pimpinan Hamas Terverifikasi

-

-