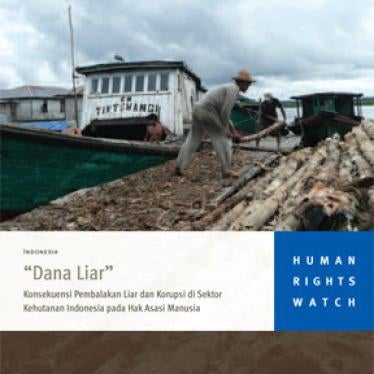(Bangkok) - Satu juta pengungsi Rohingya di Bangladesh menghadapi kecilnya kemungkinan mereka untuk kembali ke kampung halaman dengan selamat, enam tahun sejak militer Myanmar melancarkan kampanye kekejaman massal di Negara Bagian Rakhine pada 25 Agustus 2017, kata Human Rights Watch hari ini. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah gagal meminta pertanggungjawaban para jenderal Myanmar atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan genosida terhadap warga etnis Rohingya.
Lebih dari 730.000 orang beretnis Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh pada 2017 sekarang tinggal di kamp-kamp yang luas dan penuh sesak di bawah pembatasan yang semakin ketat dari pihak berwenang serta kekerasan yang terus meningkat dari sejumlah kelompok bersenjata. Sekitar 600.000 orang Rohingya tetap berada di Myanmar, yang secara efektif ditahan oleh pihak berwenang junta di bawah sistem apartheid.
"Rohingya di kedua sisi perbatasan Myanmar-Bangladesh terjebak dalam api penyucian tanpa kewarganegaraan, tanpa mendapatkan hak-hak mereka yang paling mendasar, menantikan keadilan dan kesempatan untuk pulang," kata Shayna Bauchner, peneliti Asia di Human Rights Watch. "Alih-alih menangani masalah ini secara langsung, kelambanan Dewan Keamanan PBB dan pengurangan bantuan pemerintah membuat orang-orang Rohingya semakin terpuruk."
Orang-orang Rohingya di Bangladesh dan Myanmar menggambarkan rasa putus asa yang tumbuh setiap tahun seiring dengan meningkatnya pembatasan dan memburuknya kondisi di kedua sisi perbatasan, sebagaimana diungkap Human Rights Watch.
Sejak kudeta militer 1 Februari 2021 di Myanmar, pasukan keamanan telah menangkap ribuan orang Rohingya karena "melakukan perjalanan tanpa izin" dan memberlakukan pembatasan pergerakan baru dan pemblokiran bantuan di kamp-kamp dan desa-desa yang dihuni orang-orang etnis Rohingya. Pelanggaran sistematis yang junta lakukan terhadap orang Rohingya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa apartheid, penganiayaan, dan perampasan kebebasan. Lebih dari tiga bulan sejak Topan Mocha yang mematikan menghantam Negara Bagian Rakhine, junta terus memblokir bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa, termasuk perawatan medis yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang terkena wabah demam berdarah dan malaria.
Para pengungsi Rohingya di Bangladesh menggambarkan adanya hambatan baru dalam hal pendidikan, mata pencarian, dan pergerakan yang serupa dengan pembatasan yang mereka hadapi di Myanmar. Pihak berwenang Bangladesh juga telah memindahkan sekitar 30.000 orang Rohingya ke pulau lumpur terpencil Bhasan Char, di mana mereka menghadapi pembatasan pergerakan serta kekurangan makanan dan obat-obatan.
Tanpa status hukum yang diakui di Bangladesh, para pengungsi Rohingya berada dalam posisi tidak aman di bawah hukum domestik, membuat mereka rentan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia. "Kami telah kehilangan enam tahun di sini," kata seorang perempuan Rohingya kepada Human Rights Watch. "Saya ini manusia. Mengapa saya diperlakukan seperti ini sepanjang hidup saya? Jutaan pemikiran semacam ini melintas di pikiran saya setiap hari."
Di tengah meningkatnya kekerasan yang dilakukan kelompok-kelompok bersenjata dan geng-geng kriminal di kamp-kamp pengungsian, pihak berwenang Bangladesh gagal memberikan perlindungan, menjaga keamanan, atau mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab. Para pengungsi melaporkan bahwa mereka menghadapi berlapis-lapis hambatan untuk mendapatkan bantuan polisi, hukum, dan bantuan medis.
Pihak berwenang Bangladesh telah memberlakukan sejumlah pembatasan pada sekolah-sekolah yang dikelola masyarakat sejak Desember 2021. "Situasi pengungsian yang berkepanjangan, kurangnya akses ke pendidikan dan pekerjaan, serta kekerasan yang terus berlanjut membuat kami putus asa," kata seorang pemimpin komunitas Rohingya. "Kami berjuang untuk mencari jalan keluar. Kami ingin membangun kehidupan yang lebih baik tetapi tidak bisa. Keterbatasan pendidikan menghalangi kami untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Kesenjangan pendidikan di komunitas kami semakin melebar."
Pihak berwenang kamp baru-baru ini kembali melecehkan dan mengusir sejumlah pemilik toko asal etnis Rohingya, termasuk menghancurkan toko mereka, sebuah praktik yang dimulai pada Desember 2021. "Pertama mereka mengelilingi kami dengan pagar, sekarang mereka menutup usaha kecil kami dan menghentikan kami pergi ke luar untuk bekerja," kata seorang pengungsi. "Mereka juga menghentikan kendaraan lokal untuk beroperasi di kamp-kamp, yang merupakan satu-satunya cara bagi beberapa orang tua, perempuan hamil, dan orang-orang dengan kegentingan medis untuk bergerak. Sekarang kami harus berjalan kaki sejauh empat sampai lima kilometer demi mengambil jatah makanan."
Rencana Tanggap Bersama PBB 2023 untuk krisis kemanusiaan Rohingya telah menerima kurang dari sepertiga dari US$876 juta yang diharapkan dari sumbangan para donor. Kekurangan dana telah menyebabkan Program Pangan Dunia (WFP) memotong jatah makanan bagi warga Rohingya hingga sepertiganya sejak Februari lalu, dari $12 menjadi hanya $8 per bulan, sehingga memperburuk kekurangan gizi, penyakit, dan keputusasaan di antara para pengungsi. Warga Rohingya dan pekerja kemanusiaan melaporkan bahwa pemotongan jatah makanan itu sudah menimbulkan dampak medis dan sosial.
"Dengan adanya pemotongan jatah makanan, kami tidak punya cukup makanan untuk kami sendiri," kata seorang sukarelawan Rohingya. "Pikirkan tentang anak-anak kecil di keluarga kita atau para perempuan hamil. Mereka semua terkena dampaknya."
Para donor, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan Australia, semestinya meningkatkan pendanaan dan tekanan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi Rohingya. Seharusnya mereka mendesak Bangladesh untuk mencabut pembatasannya sehingga para pengungsi memiliki akses ke alat-alat yang diperlukan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Negara-negara juga seharusnya meningkatkan peluang permukiman kembali bagi warga etnis Rohingya, terutama mereka yang jadi sasaran kelompok-kelompok bersenjata, yang tidak hanya takut pada penganiayaan di kampung halamannya di Myanmar, melainkan juga ancaman terhadap kehidupan mereka di kamp-kamp pengungsian.
Prospek pemulangan sukarela yang langgeng semakin jauh dari harapan sejak kudeta militer di Myanmar, yang dilakukan oleh para jenderal yang sama yang mendalangi kekejaman massal 2017.
Pihak berwenang Bangladesh berpendapat bahwa pemulangan orang-orang Rohingya adalah satu-satunya solusi. Pemerintah telah memulai langkah-langkah dengan junta Myanmar untuk mengembalikan warga etnis Rohingya itu ke Negara Bagian Rakhine di bawah proyek percontohan yang telah ditandai dengan pemaksaan dan penipuan.
Seharusnya PBB dan pemerintah negara-negara yang peduli terus menggarisbawahi bahwa kondisi untuk pemulangan orang-orang Rohingya yang aman, berkelanjutan, dan bermartabat saat ini belum ada. Para pengungsi Rohingya secara konsisten mengaku ingin pulang, tetapi hanya jika keamanan, akses ke tanah dan mata pencarian, kebebasan bergerak, dan hak-hak kewarganegaraan mereka dapat dipastikan. "Angka pengungsian telah menguji ketahanan dan kekuatan kami selama enam tahun ini," kata seorang pengungsi. "Saya punya impian untuk kembali ke negara saya sendiri, Myanmar, ke desa dan rumah saya, dengan hak kewarganegaraan yang penuh dan segala sesuatu yang layak didapatkan seorang manusia."
Tanggapan internasional terhadap kekejaman 2017 terkotak-kotak dan terhenti, di mana Dewan Keamanan PBB hanya melakukan sedikit hal selain mengeluarkan beberapa pernyataan. Dewan seharusnya mengambil tindakan nyata dan bermakna, termasuk melembagakan embargo senjata global, merujuk situasi negara tersebut ke Mahkaman Pidana Internasional (ICC), dan menjatuhkan sanksi terhadap kepemimpinan junta dan perusahaan-perusahaan milik militer.
"Melanjutkan pemulangan orang-orang Rohingya sekarang sama saja dengan mengirim para pengungsi itu kembali ke kendali junta yang kejam dan represif, yang akan membuka jalan bagi eksodus besar-besaran berikutnya," kata Shayna Bauchner. "Menciptakan kondisi yang memungkinkan kembalinya warga etnis Rohingya secara sukarela, aman, dan bermartabat akan membutuhkan tanggapan internasional yang terkoordinasi guna membangun pemerintahan sipil yang menghormati hak-hak di Myanmar dan mencapai keadilan atas kekejaman masa lalu."