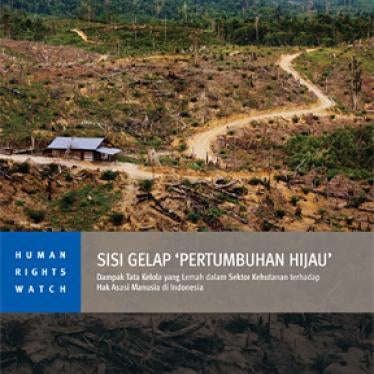Para perempuan Tiongkok telah lama berjuang demi kesetaraan. Pada Oktober 1911, kelompok revolusioner di Tiongkok selatan menggulingkan Dinasti Qing, mengakhiri sistem kekaisaran dan mendirikan Republik Tiongkok. Di antara kalangan revolusioner itu ada sekelompok aktivis hak-hak perempuan. Tapi ketika Konstitusi Sementara disahkan pada Maret 1912, tidak ada penyebutan jenis kelamin atau gender. Dikatakan, "warga negara Republik Tiongkok harus setara di depan hukum, tanpa perbedaan ras, kelas atau agama.”
“Selama pemberontakan bersenjata, perempuan ... mempertaruhkan nyawa dan harta benda mereka . . . sama seperti para laki-laki. Bagaimana mungkin sekarang saat revolusi telah tercapai tetapi kepentingan perempuan tidak diperhitungkan?” seorang feminis menuntut ketika mengetahui bahwa perempuan tidak akan diberikan hak suara yang sama ketika undang-undang pemilu yang baru diumumkan pada Desember 1912.
Para feminis masa kini di Tiongkok tahu dari pengalaman panjang untuk mewaspadai klaim laki-laki bahwa mereka mendukung persamaan hak, tidak peduli mereka adalah pejabat pemerintah atau intelektual dan aktivis liberal.
Gerakan #MeToo di Tiongkok telah mengirimkan gelombang kejut melalui lingkaran progresif karena beberapa laki-laki yang dituduh melakukan kekerasan dan pelecehan seksual adalah para intelektual dan aktivis terkemuka yang telah lama memperjuangkan kesetaraan hak. Para lelaki terkemuka yang dituduh berperilaku kasar termasuk aktivis anti-diskriminasi Lei Chuang, aktivis lingkungan Feng Yongfeng dan jurnalis Xiong Peiyun. Lei dan Feng mengakui tuduhan itu, sementara Xiong menyangkalnya.
Zhang Wen, seorang jurnalis terkenal yang dituduh melakukan pemerkosaan dan pelecehan oleh beberapa perempuan, menyerang para penuduhnya karena “diceraikan” dan “memiliki banyak pacar lelaki.” Dia juga mengancam akan menuntut mereka yang melontarkan tuduhan terhadapnya.
Seperti kebanyakan orang dalam masyarakat Tiongkok, beberapa intelektual dan aktivis lelaki biasa menyebut rekan-rekan perempuan mereka “perempuan cantik” atau “dewi” dan mengunggah foto perempuan muda berpakaian minim di media sosial. Dalam kampanye untuk mengumpulkan uang bagi keluarga aktivis yang ditahan, penyelenggara Rou Tangseng menggunakan foto kaki telanjang perempuan untuk menarik sumbangan. Saya pernah disebut “dewi” oleh seorang aktivis lelaki ketika saya mengkritik penahanan para pembangkang politik oleh pemerintah Tiongkok - tetapi orang yang sama menyebut saya “seorang perempuan jelek yang tidak diinginkan lelaki manapun” ketika saya mengangkat isu diskriminasi gender dalam masyarakat Tiongkok.
Sekarang sesuatu yang baru muncul dari #MeToo: Beberapa lelaki intelektual liberal yang pada masa lalu tidak terlalu memperhatikan isu hak-hak perempuan telah menyerukan refleksi diri dan dukungan bagi hak-hak perempuan.
“Saya punya banyak momen saat berperilaku mabuk dan tidak senonoh,” tulis komentator politik Mo Zhixu. “Jika saya diekspos, saya akan mengerti, ini bukan hanya tentang isu citra moral. Tingkah laku saya di masa lalu, sesungguhnya, adalah ejekan besar atas pencarian saya atas hak, kebebasan, kesetaraan, dan demokrasi. Jika saya tidak bisa menghadapi ini dengan kejujuran, itu hanya akan menjadikan pencarian saya itu sebagai sebuah lelucon.”
Penulis Zhao Chu menjelaskan bahwa sebagai orang yang sangat peduli dengan urusan hak-hak, ia harus mendukung gerakan #MeToo: “Bahkan jika. . . [Itu] artinya saya, sebagai seorang laki-laki, harus mengubah perilaku dan cara berpikir saya, bahkan jika perubahan semacam ini sangat sulit.”
Penulis feminis Li Sipan menyatakan bahwa “keajaiban telah terjadi” ketika dia melihat di media sosial banyak pesan-pesan pro-feminisme yang diunggah oleh orang-orang yang dianggapnya sebagai teman “lelaki straight yang biasa-biasa saja.”
Perubahan ini telah didorong oleh banyak perempuan Tiongkok secara online - yang umumnya berusia muda dan berpendidikan - yang dengan berani bicara, menceritakan kisah-kisah mereka, mengartikulasikan ide-ide feminis dan dengan penuh semangat mendebat sejumlah intelektual laki-laki terkenal, semuanya di tengah penyensoran pemerintah yang meluas.
Jangan mengharapkan kebangkitan yang sama dalam waktu dekat di kalangan elit politik. Setelah Presiden Xi Jinping secara resmi mengambil alih kekuasaan pada tahun 2013, pemerintah mengencangkan cengkeramannya pada masyarakat sipil, termasuk feminis. Pada Maret 2015, pihak berwenang menahan lima aktivis hak perempuan selama sebulan setelah mereka berencana membagikan stiker dengan pesan anti-pelecehan seksual di bus umum. Maret ini, platform media sosial Tiongkok Weibo dan WeChat secara permanen menangguhkan akun Suara Feminis, sebuah publikasi hak-hak perempuan.
Pada bulan Juni, Ren Liping, seorang mahasiswa di China University of Petroleum, ditahan selama enam hari di sebuah kamar hotel oleh pihak kampus setelah dia memprotes universitas dan polisi karena salah menangani dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. Ren menuduh mantan pacarnya memperkosa dia di kampus.
“Generasi muda aktivis hak-hak perempuan ... memiliki kepribadian mandiri yang kuat,” kata profesor feminis dan sastra Ai Xiaoming. “Kepribadian independen semacam itu telah ditanamkan . . . menjadi semangat untuk gerakan hak-hak perempuan saat ini di Tiongkok.”
Meski ruang untuk aktivisme masyarakat sipil dalam bentuk apa pun menyempit di Tiongkok saat ini, kelompok feminis telah dengan berani dan kreatif mengikuti jalan leluhur feminis mereka sejak lebih dari 100 tahun lalu. Mereka mengabaikan resiko dari target kembar mereka yaitu negara otoriter dan masyarakat patriarkal.