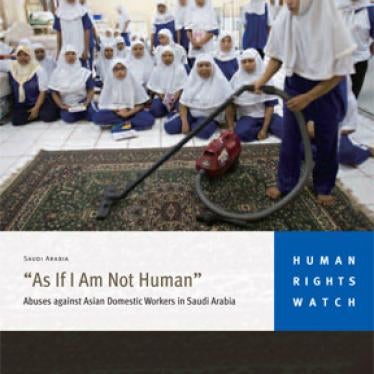Namun air pasang mungkin mulai bergeser, dengan berbagai inisiatif yang sedang berjalan dan meletakkan landasan bagi masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah yang lebih aktif untuk menekan otoritas Israel terhadap kewajiban mereka sesuai hukum internasional. Prancis dapat memimpin di sini dan Macron seharusnya menggunakan pertemuannya dengan Netanyahu ini untuk memperjelas bahwa akan ada konsekuensi bagi Israel yang terus mengabaikan hak asasi manusia.
Bulan lalu, Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman menyetujui pembangunan 2.500 unit rumah baru di permukiman di Tepi Barat yang diduduki, tempat tinggal lebih dari 600.000 pemukim Israel saat ini. Pemindahan warga sipil ke wilayah pendudukan merupakan kejahatan perang. Permukiman juga berkontribusi pada rezim diskriminatif, yang memperlakukan orang Palestina secara terpisah dan tidak setara.
Pada Maret 2016, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui pembuatan dan publikasi basis data kegiatan bisnis di permukiman. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM berharap bisa menerbitkan versi awal dari basis data itu pada bulan Agustus ini. Uni Eropa juga baru-baru ini menerapkan sejumlah peraturan yang mewajibkan pelabelan impor dari permukiman, sehingga Israel tidak dapat menyamarkan barang-barang asal permukiman sebagai buatan Israel. Prancis telah memasukkan peraturan ini ke dalam hukumnya sendiri. Macron seharusnya mengingatkan Netanyahu tentang penentangan Prancis terhadap permukiman, dengan memperjelas bahwa Prancis akan terus mendukung basis data di tengah upaya beberapa pihak untuk menekan penerbitannya dan menyarankan perusahaan Prancis untuk tak lagi berbisnis di atau dengan wilayah permukiman.
Untuk memfasilitasi perluasan permukiman dan sarana pendukungnya, pemerintah Israel telah mengambil alih ribuan hektar tanah Palestina dan menghancurkan rumah dan bangunan milik warga sipil seperti sekolah dengan alasan mereka tidak memiliki izin, meski beban diskriminasi menjadikannya nyaris mustahil bagi orang Palestina untuk mendapatkan izin seperti itu di Yerusalem Timur dan 60% dari Tepi Barat di bawah kendali eksklusif Israel (dikenal sebagai "Area C" sejak Perjanjian Oslo).
Pada 24 Mei, Mahkamah Agung Israel menyetujui rencana pemerintah untuk menghancurkan Khan al-Ahmar Ab al-Hilu, sebuah desa berpenduduk 180 orang di timur Yerusalem, termasuk sekolahnya, yang mendidik 160 anak dari lima desa di sekitarnya. Sekolah ini hanya satu dari puluhan sekolah Palestina yang mendapat perintah pembongkaran dari militer Israel dan Khan al-Ahmar hanyalah salah satu dari 46 komunitas Palestina yang dianggap PBB "berisiko tinggi mengalami pemindahan paksa." Pemindahan paksa peduduk di wilayah yang diduduki adalah kejahatan perang.
Uni Eropa, para pejabat PBB dan Menteri Inggris untuk urusan Timur Tengah dan Afrika Utara telah memperingatkan Israel agar tidak menghancurkan Khan al-Ahmar, yang bisa terjadi kapan saja. Negara-negara Eropa juga baru-baru ini bergerak dan tidak hanya sekadar mengecam; pada Oktober 2017, delapan negara, termasuk Prancis, menuntut kompensasi atas bangunan kemanusiaan yang mereka bantu bangun di Area C dan yang dihancurkan Israel. Macron seharusnya secara terbuka meminta Netanyahu agar membatalkan rencana penghancuran Khan al-Ahmar dan menjelaskan bahwa Prancis akan terus mendukung upaya internasional untuk mengidentifikasi dan menuntut mereka yang bertanggung jawab atas kemungkinan kejahatan perang.
Sejak 30 Maret, pasukan Israel membunuh lebih dari 100 warga Palestina dalam aksi-aksi demonstrasi di Gaza dan melukai ribuan orang lainnya; korban terakhir adalah paramedis perempuan bernama Razan al-Najjar (21 tahun) yang ditembak mati pada 1 Juni, meski teridentifikasi jelas sebagai sukarelawan medis dan karena dia tampak merawat pengunjuk rasa yang terluka. Pembunuhan itu terjadi ketika tentara melaksanakan perintah dari pejabat senior Israel untuk menembak, yang memungkinkan mereka untuk menggunakan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa, di luar situasi di mana mereka bisa menimbulkan ancaman segera terhadap nyawa, bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum. Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di tengah-tengah satu dasawarsa penutupan Gaza, yang sangat membatasi pergerakan orang dan barang, dan diperburuk oleh Mesir yang menutup sebagian besar perbatasannya dengan Gaza.
Pada 17 Mei, Dewan HAM PBB membentuk Komisi Penyelidikan untuk menyelidiki pembunuhan di perbatasan Gaza. Jaksa di Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang melakukan pemeriksaan awal terbuka terhadap situasi di Palestina, mengatakan bahwa kantornya mengikuti perkembangan di Gaza. Upaya-upaya ini bertujuan untuk mendobrak impunitas virtual dalam sistem peradilan Israel yang memungkinkan terjadinya pelanggaran semacam itu.
Seiring meningkatnya pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Israel, mereka juga terus mempersempit ruang bagi para pembela HAM. Bulan lalu, Israel mencabut izin kerja Human Rights Watch dan memerintahkan agar saya meninggalkan negara itu. Keputusan, yang menurut Israel didasarkan pada posisi saya yang diduga melakukan boikot terhadap Israel sebelum bergabung dengan Human Rights Watch (meski mengakui bahwa baik organisasi maupun saya sebagai perwakilannya tak mempromosikan boikot), muncul ketika pemerintah Israel mempersulit kelompok-kelompok HAM untuk bekerja, menuduh kelompok-kelompok advokasi Israel memfitnah dan mendiskreditkan negara dan tentara serta memberlakukan pembatasan perjalanan, dan bahkan menangkap serta mengajukan tuntutan pidana bagi para pembela HAM Palestina.
Berbagai suara, termasuk dari Uni Eropa dan PBB, telah mengeluarkan pernyataan tegas yang mendukung Human Rights Watch, yang sedang melakukan banding atas pencabutan izin kerja di pengadilan Israel. Selain itu, para pejabat asing terus bertemu dengan kelompok-kelompok hak asasi di Israel dan Palestina, meski ada peringatan dari pemerintah Israel. Macron seharusnya menyatakan keprihatinannya soal meningkatnya pembatasan terhadap pembela HAM Palestina, Israel, dan internasional.
Peningkatan momentum internasional untuk memerangi pelanggaran HAM Israel, bagaimanapun, terancam oleh munculnya para pemimpin populis di seluruh dunia yang menyerang nilai-nilai universal. Prancis memiliki peran penting dalam membela HAM dan hukum internasional pada saat kritis ini. Negara ini seyogianya merebut peluang bersejarah ini sebelum makin banyak peringatan yang suram berlalu.